
Di Rangkum Kembali oleh Tryas Munarsyah ST dari Tulisan” Irawan Santosso Shadiq
Khalayak masih disuguhi mimpi demokrasi. Dari siklus Polybios kita bisa menarik bukti. Ini bukan lagi masa demokrasi. Karena fase itu telah lewat jauh. Ini jaman model okhlokrasi. Dr. Ian Dallas, penulis ulung asal Skotlandia, memberi tunjuk ajar dalam The Entire City, kitabnya termahsyur.
Demokrasi jelas telah mati. Lihatlah masa Romawi. Di sanalah demokrasi pernah dilakoni. Longoklah masa Yunani kuno. Jamannya Aristoteles merumuskan. Era sebelum Plato menggambarkan, “republik.’ Athena kemudian berubah dengan ‘demokrasi.’ Romawi masa Cicero memberi gambarannya. Masa Julius Caesar berjaya. Saat itulah suasana demokrasi bisa dinikmati. Tapi selepas itu, bencana tiba. Masuk ke fase okhlokrasi. Sekali lagi, Dallas memberikan gambaran utuh dalam ‘The Entire City.’
Karena kini bukan lagi demokrasi. Tak perlu dibahasa panjang lebar. Karena siklus telah terbukti. Okhlokrasi inilah fasenya. Jamannya. Sistemnya telah berjalan. Karena demokrasi telah lewat. Teori ‘Trias Politica-nya Montesquei telah lenyap. Itu hanya angan-angan belaka. Karena susunan kekuasaan bukan sekedar ‘eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bukan itu. Selepas revolusi Perancis, 1789, teori itu langsung gugur. Karena tak sesuai dengan amalannya.
Fase itulah muncul yang namanya ‘state’. Ini dari bahasa Machiavelli. Il Principe menyebutnya ‘lo stato.’ Alenia pertama kitab ‘Sang Pangeran’ itu. Dari ‘lo stato’, diterjemahkan menjadi ‘state’ dalam english. Perancis diterjemahkan ‘L’etat’. Belanda jadi ‘staat’. Inilah diterjemahkan menjadi ‘negara.’ Entah pas atau tidak padanannya. Tapi fase itulah seolah demokrasi didengungkan.
Selepas kudeta pada ‘Vox Rei Vox Dei” di Eropa klasik. Suara Raja Suara Tuhan dikudeta. Diganti suara rakyat suara Tuhan. Demokrasi seolah menjadi dibela sampai mati. Padahal terjadi penyelewengan. Karena dibalik ‘Vox populi vox Dei’, menyelesup sekelompok orang penentu. Mereka yang menyusun ‘state’ tadi. Merekalah kaum bankir. Pemilik bank sentral. Dan bank sentral menjadi makhluk ‘ghaib’ diluar ‘Trias Politica.’ Tak dikenali Montesquei. Tak dikenali Machiavelli. Tapi menyelusup dalam teorinya JJ Rosseou. Inilah wujud ‘state’ yang nyata. Bukan lagi ‘Trias Politica.” Melainkan ‘Trias Politica’ dikendalikan ‘sentral bank.’
Karena faktanya sentral bank memiliki kekuasaan. Mereka mengendalikan uang. Mengendalikan harta. Mereka entitas yang tak bertanggungjawab secara hukum pada entitas ‘Trias Politica.’ Mereka berdiri sendiri. Utuh, mandiri tanpa pengawasan. Karena gouverment bukan sebagai ownernya. Melainkan dimiliki segelintir kaum Yahudi. Sekuel itu bisa dibaca melalui Bank of England, 1668. Kala bank sentral pertama di dunia itu berdiri, mengendalikan Raja William sebagai nasabah terbesar. Raja Inggris berutang pada bank.
Sekuel itu kembali berulang. Kaum bankir mengkooptasi Perancis. Mengkudeta Raja Louis XVI. Dan membentuk ‘republik’ Perancis. Disitulah sekuel okhlokrasi dimulai, bukan lagi demokrasi. Bankir mengangkat Napoleon. Napoleon jadi Kaisar Perancis. 75 borjuis Perancis mengangkatnya. Napoleon tak lagi dilantik oleh Gereja Roma. Tapi oleh kaum bankir, oligarkhi. Mereka memberikan utang berbunga pada sang Kaisar. Pasca mereka mengkudeta Robbiespierre, pemimpin revolusi. Karena Robiespierre, tak mau tunduk pada oligarkhi bankir. Lalu Napoleon jadi raja. Tapi bankir itu meminta jatah: mengatur kendali kerajaan Perancis baru. Berdirinya “Bank de France” sebagai Sentral bank. Entitas ini kerap hadir dalam state modern.
Di kemudian hari menggulingkannya. Seabad kemudian, mereka merambah Daulah Utsmaniyya. Tanzimat 1840, periode masuknya ‘okhlokrasi’ di Utsmaniyya. Aksi Attaturk 1924, menjadi kelanjutannya. Tapi ‘okhlokrasi’ merambah dimana-mana. Tak ada ‘trias politica.” Tak ada yang disebut demokrasi. Karena raklyat tak memegang kendali. Kendali dibawah kontrol banking sistem. Disitulah rusaknya mekanisme peradaban manusia. Tak lagi fitrah.
Fenomena ‘state’ merambah seantero dunia. Disitulah Dallas memberi kita lagi Harold Laski, lawyer Inggris abad 20. Laski berbicara tegas dalam ‘Vindiciae Contra Tyranoss.’ Dia berkata, “Saatnya re-evaluasi terhadap konsep ‘state’.” Kalimat Laski ini layak dipedomasi. Karena sejak itulah fase okhlokrasi dimulai.
Fakta sejarah dunia, ‘state’ bukan didirikan oleh ‘the founding fathers’. Melainkan oleh segelintir bankir. State Mesir, Turki, disana berperan Ernst Cassel, pemilik Bank of Egipt dan Bank of Istanbul. Tentu layak disimak, benarkah Amerika Serikat didirikan Abraham Lincoln. Karena di sana peranan bankir merajalela. Merekalah penentu berdirinya ‘state’, seperti fase Inggris dan Perancis pasca revolusi 1789. Inilah sekuel historis yang tak dirambah bangku kuliah. Tapi fenomena nyata dalam kisah sekarang. Karena tak satu pun gouverment state bisa mencetak uangnya sendiri. Melainkan di bawah otoritas banking sistem. Dari sini teori ‘soverignity’ Jean Bodin jelas gugur. Apalagi merujuk pada ‘Leviathan’nya Thomas Hobbes. Seolah ini menjadi kenyataan. Makhluk buas yang menguasai dunia, dalam perspektif yang bukan ditawarkan Hobbes. Melainkan perspektif yang memperbudak manusia modern.
Karena tatanan dunia kini dikendalikan kaum bankir. Bukan oleh rakyat. Kehendak rakyat sama sekali lumpuh. Rakyat hanya dijadikan warga buruh. Pasca revolusi Perancis, tatanan kelas masyarakat hanya terbagi dua. Ian Dallas menggambarkan utuh dalam kitabnya, “The Engine of the Broken world.” Dulu, sebelum revolusi Perancis, kaum sipil Eropa terbagi tiga kelas. Kaum bangsawan dan agamawan, kaum pengusaha dan kaum rakyat. Selepas ‘demokrasi’ merebak, berubah menjadi dua kelas saja. Kelas penguasaha (majikan), kedua kedua menjadi kosong, dan rakyat tetap di kelas ketiga. Inilah tatanan dunia. Kaum pengusaha mengkudeta bangsawan dan agamawan. Gereja dan Raja dikudeta. Bankir yang kemudian berkuasa. Inilah fase okhloktrasi itu. Bukan demokrasi.
Ini juga yang disebut era modernisme. Dan kini berubah menjadi post modernisme. Dalam perspektif uang, nampak kasat mata pergeserannya. Dulunya, semua manusia menggunakan emas dan perak. Kemudian diubah menjadi kertas, oleh para bankir dan state-man. Itulah fase modernitas. Lalu kini uang berubah lagi menjadi byte komputer, atas dasar hukum positvisme. Ini yang disebut post modernisme. Tentu, kendali itu semua bukan pada ‘head of state.’ Bukan pada kepala negara. Melainkan pada banking sistem. Yang dikontrol segelintir Yahudi kaya. Mereka lintah darat, rentenir yang sejak masa Perang Salib berbisnis tukar menukar uang. Kemudian memiliki nasabah seorang Raja. Dan kemudian mengganti raja menjadi ‘presiden’ atau ‘perdana menteri.’
Dari sinilah okhlokrasi terbaca. Tatanan dunia kini, yang bukan lagi demokrasi. Nietszche, filosof fenomenal mampu memberi jawaban. Bahwa tatanan ini bukan lagi ‘kebenaran’ hakiki. Itu yang dia sebut dengan ‘nihilisme.’ Hilangnya nilai-nilai manusia. Karena kemusyrikan telah melanda manusia. Itu dimulai sejak era rennaisance, filsafat dilahap Eropa, mengambil dari mu’tazilah tentunya.
Dari situlah tatanan dunia berubah. Filsafat, kemudian melahirkan filsafat kekuasaan. Lahirlah ‘politik. Filsafat kemudian merumuskan tentang hukum, lahirlah ‘positivisme.’ Dan sialnya, kaum muslimin abad modern, ikut terkesima. Ikut-ikutan kuffar dengan merumuskan Islam. Alhasil lahirlah ‘Islamisme.’ Teori tentang Islam. Tentu ini bukan Dinul Islam.
Yang pasti, ini bukan lagi demokrasi. Tentu tak layak bicara ‘demokrasi’ juga sesuai Islam. Melainkan harus mahfum membaca jaman. Karena selepas okhlokrasi, akan kembali pada monarkhi. Kepemimpinan yang melekat pada personal rule. Bukan lagi system rule. Dr. Ian Dallas telah memberikan tuntas
Riba telah menjadi system. Dari negara sampai keluarga, terjerat utang berbunga. Bunga berbunga. Ini dikata riba majemuk. Modernisme itulah yang mengenalkan system riba. Bahasa lainnya, kapitalisme. Kaum oligarkhi, tentu nyaman dengan system riba. Karena model riba, hanya berlaku dua posisi: debitur dan kreditur. Lex Divina melarang pola ini.
Ternyata aturan hukum melegalkan. Mekanisme utang berbunga, terpatri dalam aturan hukum. Nusantara mulai mengenalnya sejak masa penjajahan. Hindia Belanda membawanya. Mereka mengadopsi Code Napoleon. Isinya tiga kitab hukum induk: Code Penal, Code, Civil, dan Code de Commerce. Azas konkordansi yang dianut Hindia Belanda, mengekspor aturan ini sampai ke nusantara. Aturan legalisasi riba, terpatri dalam Code Civil itu. Belanda menterjemahkannya menjadi Burgelijk Wetboek. Inilah yang kemudian menjadi KUH Perdata. Sampai sekarang tak pernah diubah. Murni diadopsi. Ini aturan yang asalnya dari Code Napoleon. Napoleon memberlakukannya sejak pasca Revolusi Perancis, 1789. Apa itu revolusi Perancis? Ini perang aqidah di Eropa. Antara pengikut patriotisme melawan pengikut dogma Gereja Roma. Mereka tak lagi tunduk pada aturan Tuhan. Melainkan mencari hukum rasio, yang sumbernya bukan kitab suci. Karena telah menggantung Raja Louis XVI. Raja disimbolisasi sebagai “wakil Tuhan” dalam era pra revolusi. Vox Rei Vox Dei. Suara Raja suara Tuhan.
Tak ada lagi trias politica ala Montesquei. Itu basi. Karena central bank yang sejatinya “penguasa” yang mengendalikan sebuah ‘state modern.’ Stendhal, sejarawan Inggris berkata, sesiapa mengendalikan harta, dialah penguasa. Karena tak ada penguasa tanpa mengendalikan harta. Simbol harta yang utama adalah uang. Jadi siapa mengatur system uang, dialah yang berkuasa. Terbukti, pemimpin-pemimpin modern state, tak satupun berdikari mengendalikan ‘uang’ dalam negaranya. ‘Currenzy’ tak diatur oleh senat. Dari Amerika kita bisa lihat, kurs mata uang, tak lahir dari “beschikking” Gedung Putih. Melainkan berada dalam kekuasaan The Federal Reserve Bank. Pola ini yang berlangsung seantero dunia kini.
Ini memuncak dari pasca Perang Dunia II. Setelah revolusi Perancis, bankir terus menggeliat mengekspor pahamnya. Mengekspor dan memaksa mekanisme keuangan dan kekuasaannya. Hingga mereka mengatur perang antar negara. Musuh mereka cuma satu: entitas agama. Revolusi Perancis, mereka menghancurkan entitas Nasrani. Tak ada lagi kedigdayaan Gereja Roma. Lalu setelahnya merambah ke negeri-negeri muslim. Jadilah Daulah Utsmaniyya, diobok-obok dari luar dan dalam. Senjata mereka adalah filsafat. Karena rasio mudah dikooptasi. John Locke pernah berpesan, “Wahyu tetap diperlukan karena ada yang kerap menyalahgunakan akalnya.” Modernisme inilah fakta betapa reason law, berubah menjadi akal-akalan. Wujudnya bisa dilihat sekarang.
Lalu, dirancang ideologi positivisme. John Austin, sampai Auguste Comte jadi pondasi. Hans Kelsen menjadi dukun utama teori ‘hukum murni.’ Positivisme seolah harga mati. Reason law mengkudeta natural law. Revolusi Perancis itulah kemenangan awal “positivism.” Tak ada lagi Lex Divina. Yang ada hanya –merujuk Thomas Aquinas menyebutnya– lex aeterna. Hukum setan.
Dari ideologi itulah menusuk masuk legalisasi riba. Oligarkhi bankir berkepentingan Supaya utang harus berbunga. Mereka telah punya nasabah para head of state. Kejadian Bretton Wood, 1946, itu jadi bukti. Para “head of state” dibawah oligarkhi bankir. Mereka tunduk dan patuh bahwa urusan ‘uang’, sepenuhnya dibawah kendali bankir. Makanya “Gedung Putih” tak bisa mengendalikan kurs Dollar. Maka, kala George Washington mengklaim Amerika adalah negara Republik jelmaan Romawi, tentu dia keliru jauh. Washington tak melihat bagaimana konsep Republik yang sejati.
Bicara Republik, ini kosakata dari Yunani Kuno. Cicero menterjemahkannya dalam kitabnya “Republik.” Cicero (106-43 SM), tokoh besar Romawi sejaman Julius Caesar, menuliskan tentang Bagaimana republik harus dijalankan. Masa itu, riba juga telah dikenal. Mereka menyebutnya ‘usury’. Pelaku riba, selalu hadir setiap jaman. Karena mereka kerap tunduk patuh pada ‘lex aeterna.’
Romawi juga memusuhi riba. Geliat oligarkhi, pebisnis uang, mulai tampak juga meresahkan republik. Cicero menganggap perilaku ‘riba’ itu tak sesuai dengan konsep negara republik. Dalam bukunya: The Officis”, Buku II, Cicero menegaskan kebenciannya pada riba. Dalam dialognya dengam Cato, Cicero menguraikan, “Apa yang dikatakan tentang mencari keuntungan dengan riba?” Cato menjawab, “Apa yang dimaksud dengan menghasilkan keuntungan dengan membunuh?” Cicero menegaskan, mencari keuntungan dengan riba, itu sama saja dengan mencari untung dari pembunuhan. Karena riba sangat kejam. Begitulah cara pandang Cicero, konseptor Republik, era Romawi. Memungut riba, perbuatan yang keji.
Dalam bukunya “Republik,” Cicero lebih tegas lagi. “Leluhur kita punya metode sendiri dalam memulihkan masalah utang. Solon, dari Athena, telah lebih dulu menemukannya. Tapi senat tak mengadopsinya. Yaitu ketika muncul perilaku kreditur yang buruk, seluruh penduduk dibebaskan akibat penindasan utang…”
Itu kata Cicero. Dia tegas, pelaku riba –kreditur yang buruk—harus dilawan. Senat harus memimpin kebijakan, bahwa penduduk harus dibebaskan dari penindasan utang. Begitulah Republik menurut Cicero. Republik adalah anti riba. Dalam Republik, tak diperkenankan adanya kreditur yang menindas. Kejadian Napoleon di bawah kendali bankir, bisa dilihat bagaimana formula kreditur buruk itu kini.
Lalu, longok lagi Bagaimana Republik menurut si konseptor awal. Kita bisa lihat pada masa Yunani Kuno. Karena disanalah kata “republic” diproduksi. Ini bukan kosakata nusantara. Jadi, tak ada satupun orang timur yang mahfum benar Bagaimana konsep republic. Mau tak mau kita harus lihat pada filosof Yunani Kuno. Pada Plato dan Aristoteles.
Aristoteles, dalam kitabnya “Politik”, lebih kejam dalam mengecam perilaku riba. Aristoteles menyebut, pembungaan uang adalah perbuatan jahat. “Pedagang kelas rendah itu sangat dibenci dengan alasan: ia menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri…Uang sebagai alat pertukaran: riba (usury) mencoba membuatnya bertambah.” Aristoteles menyebutnya menghasilkan “uang dari anak uang.” “Oleh karena itu, kita dapat mengerti mengapa Riba (usury) adalah hal yang paling tidak alamiah dari semua bentuk pendapatan,” kata Aristoteles. Guru dari Alexander The Great itu sangat mengecam perbuatan riba dan perilaku riba.
Begitu juga Plato. Dia memiliki kitab ‘Republik”. Dari sinilah Republik Romawi memulai. Karena terkesima konsep republic dari masa Yunani Kuno. Plato juga tak setuju dengan riba. Republik, menurut Plato, negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat dalam pengendalian diri dalam menjaga keserasian hidup bernegara. Keserasian hidup bernegara itu, menurut Plato, salah satunya harus menjaga keadilan dalam perdagangan. Dan bentuk perdagangan, tentu bukanlah riba.
Dalam kitabnya, “The Laws”, Plato mengecam keras riba. “Kami mengatakan bahwa di negara bagian tidak ada emas atau perak, juga tidak boleh ada banyak penghasil uang melalui perdagangan kasar atau riba atau penggemukan hewan gelded………….” Dari kitab itu, Plato menunjukkan ketidaksetujuannya dengan perilaku riba dalam perdagangan. Maka, riba jelas sangat tidak bersesuaian dengan bentuk negara republik.
Karena Plato, Asristoteles, Cicero, inilah konseptor bentuk negara Republik. Mereka yang memiliki modul Bagaimana Republik dijalankan. Romawi sampai sebelum era Kaisar Oktavianus, mempraktekannya.
Indonesia, mendeklarasi sebagai negara berbentuk Republik. Ini warisan dari “the founding fathers” sejak dulu. Tapi penentuan bentuk republik, dilakukan secara voting dalam sidang PPKI. Mereka berdebat tentang Bagaimana bentuk negara Indonesia kedepan: kerajaan atau republic. Hasil voting memutuskan: republik. M Yamin menjelaskan bahwa bentuk republik, seperti yang sudah diketahui umum.
Tafsir bentuk negara republik, tentu bukan merujuk pada Mpu Tantular atau Mpu Prapanca. Melainkan harus merujuk pada Plato, Aristoteles dan Cicero. Mereka yang memiliki kitab “Republik.”
Sementara Plato sampai Cicero, mereka menganggap riba adalah perbuatan kejam. Tentu itu tak sesuai dengan bentuk negara republik. Dari situ, maka bentuk negara republik haruslah memuat aturan hukum yang anti riba.
Sementara Code Civil, yang diadopsi dari Code Napoleon, dibawa Hindia Belanda menjadi Burgelijk Wetboek, inilah klausul yang banyak mengatur legalisasi pasal riba. Inilah KUH Perdata, yang sampai kini masih digunakan.
Tim Hukum Masyumi melakukan uji materil KUH Perdata berkaitan pasal riba ke Mahkamah Konstitusi. Ini untuk menyadarkan kembali bagaimana bentuk negara republik harus dijalankan. Sayang, MK berpikiran sempit. Seolah uji materil itu bentuk “intoleransi.” Padahal klausul riba dalam aturan hukum itulah bentuk intoleransi. Karena agama mengharamkan riba. Sementara Plato, Aristoteles, Cicero, mereka semua menentang riba. Merekalah yang paling tahu Bagaimana bentuk republik. Maka, republic itu haruslah anti riba. “Riba adalah tidak fitrah,” kata Aristoteles. Ian Dallas, ulama besar dari Eropa menyebutkan, “Republik adalah fitrah.” Aturan umum. Bukan “res privata.” Melainkan “res publica.”
Terbukti, kala pasal riba diadopsi, sejak VOC hingga oligarkhi, mereka yang Berjaya. Tapi Plato meyakini, “Mereka tak Bahagia,” katanya dalam “Republik.” Karena Al Quran telah menyebutkan, pelaku riba tak akan bisa berdiri tegak. Mereka seperti orang kesurupan.
Siapa yang menentukan kurs uang? Tak ada ahli tata negara yang bisa menjawab ini. Karena teori tata negara, tak mengenal perihal pengaturan kurs uang. Ini pertanda kelemahan teori ‘negara’ –sebuah teori yang mulai muncul sejak abad pertengahan–. Karena ‘negara’ (state) terbukti tak mengatur uangnya sendiri. Modern state, sebuah fenomena dimana ‘negara’ kehilangan kontrol atas uangnya. Tak ada satupun ‘head of state’, mampu mengendalikan uang yang berlaku di negerinya sendiri.
Karena tiada satupun negara, memiliki kedaulatan atas uangnya. Currenzy, mata uang, ini baru dikenal sejak pasca Perang Dunia II. Bretton Wood, 1946, menjadi pertanda kemenangan ordo Bankir. Sejarah seolah berkata, Perang Dunia II dimenangkan kaum sekutu. Tapi realitasnya, perang itu menjadi kedigdayaan Bankir atas negara-negara. Karena setelah perang genosida itu, kaum bankir memberi titah, bahwa uang yang mereka terbitkan di setiap negara, tak lagi ada back up emas.
Sejak itu pula tiada lagi kekuasaan ‘state’ atas control uangnya sendiri. John F Kennedy mencoba mengambil alih. Tapi penembakan dirinya menjadi jawaban. Karena dia berusaha mengembalikan US Dollar pada kedigdayaan emas. Bukan kertas. Moammar Khadaffi, Presiden Libya, bersikeras agar kurs uang di negaranya dikendalikan sepenuhnya. Tapi ujungnya adalah proses kudeta bagi kekuasaannya.
Tapi yang jelas, fenomena modern state, betapa negara tak berdaya atas uangnya. Realitas ini tentu berseberangan dengan teori Jean Bodin, Soverignty. Bodin, dengan tegasnya bahwa ‘state’ haruslah berdaulat penuh. Tanpa anasir-anasir pengaruh apapun. Teori Bodin itu, dikeluarkan kala eranya kekuasaan Raja, banyak dipengaruhi oleh kelompok Gereja Katolik Roma. Maka teori ‘politique’ memaksa agar kekuasaan lepas dari ‘kehendak Tuhan’. Kekuasaan berada di tangan ‘kedaulatan manusia.’ Disitulah Rosseau mencetuskan seolah ‘Vox Populi Vox Dei’ lebih baik ketimbang ‘vox Rei Vox Dei’ (Suara Raja Suara Tuhan).
Tapi ujung dari ‘kedaulatan manusia’ adalah bentuk pergantian kedudukan. Pasca Revolusi Perancis, 1789, kekuasaan elit yang sebelumnya ditangan Raja dan Gereja Roma, terkudeta oleh kekuasaan kaum borjuis. Mereka inilah cikal bakal kaum bankir. Napoleon Bonaparte didapuk menjadi Kaisar Perancis, pasca mengkudeta Robbiespiere. Tapi proses kudeta itu dilakukan sekelumit elit oligarkhi. Mereka yang mendudukkan Napoleon sebagai pemimpin Perancis.
Kemudian Napoleon diberi 75 juta Franc, sebagai utang nasional. Tapi elit bankir itu membuat konsorsium perusahaan, bahwa urusan keuangan negara Perancis baru, berada di bawah kendalinya.
Disitulah tercipta ‘Bank de France’, yang menjadi bank nasional Kerajaan Perancis baru. Ini peristiwa yang seabad sebelumnya telah dilakukan tatkala Kerajaan Inggris keluar dari liga ‘Imperium Romanum Socrum.’ Para baron, meminjamkan uang senilai 25 juta Pound, kepada Raja William, yang sengaja dinikahkan oleh Ratu Mary I. Selepas Inggris keluar dari kekuasaan Gereja Roma. Dari situlah model ‘modern state’ tercipta. Maka, Raja William dan Napoleon di Perancis, sama sekali tak memiliki kendali uang di negerinya sendiri. Bisa dikatakan, mereka hanya pemimpin yang diciptakan elit bankir.
Revolusi Perancis hanya melahirkan ordo bankir sebagai penguasa atas modern state. Merekalah kaum Yahudi, yang sejak era Isa Allaihisallam bekerja sebagai pebisnis uang. Riba. Gejolak renaissance di Eropa, yang melahirkan modernisme, dijadikan loncatan bagi kekuasaan mereka. Tapi rakyat seolah diberikan hiburan dengan slogan ‘egalite-liberte-fraternite.’ Sebuah kebebasan palsu. Karena egalite, maknanya lepas dari hukum Tuhan. Liberte, merdeka dari kekuasaan atas ‘Kehendan Tuhan.’ Dan ‘fraternite,’ persaudaraan sesame pengikut ‘kehendak manusia.’ Slogan itu yang menjadi perlindungan kaum banker untuk menciptakan new world order: modern state.
Maka, mencuatnya modern state, sama sekali bukanlah kekuasaan berada di tangan rakyat. Melainkan sepenuhnya atas kendali bankir. Mereka yang menciptakan bank sentral, mesti hadir di setiap ‘state.’ Karena sejatinya, perihal ‘separation of power’ ala Montesquei, tak dikenal dengan bank sentral. Kekuasaan atas uang, jika merujuk pada era demokrasi Romawi, maka haruslah ditangan senat. Senat yang berhak untuk mencetak uang. Tapi modern state, pencetakan dan penerbitan uang, berada di luar kekuasaan senat. Malah berada diuar kendali ‘gouverment’ itu sendiri. Realitasnya, tak ada satu pun ‘state’ yang mampu mengatur nilai uangnya sendiri. Karena naik turun nilai uang, bukan ditentukan oleh cadangan emas. Melainkan diatur oleh laptop para bankir. Itu yang disebut banking system. Sebuah aturan yang disusun manusia, pasca revolusi industry. Karena industry paling top era modern adalah perbankan. Menjual uang, dengan tanpa modal apapun. Maka, slogan orang kaya, bukanlah siapa yang paling besar memiliki tambang, ataupun perusahaan sawit. Tapi merekalah para pemilik bank. 10 daftar nama orang terkaya setiap negara, itu hanya pengelabuan wujud mereka. Karena kaum bankir nyaris tak dikenal, tapi mereka memiliki kekuasaan atas kendali uang.
Modernisme ini memberi fakta, tak ada yang namanya ‘soverighnty’ seperti teori Bodin. Apalagi ‘trias politica’ ala Montesquei. Karena ‘central bank’ menjadi pilar keempat, yang independen dibanding eksekutif, legislative maupun yudikatif. Sentral bank memiliki kedudukan istimewa dalam ‘state.’ Walhasil, fenomena ‘kurs uang’ dan ‘utang nasional’, menjadi bagian tak terpisahkan dari modern state. Revolusi Inggris dan Revolusi Perancis- lah yang bisa memberi jawab mengapa hal itu bisa terjadi.
Fakta inilah yang disebut Dr. Ian Dallas, ulama besar dari Eropa, bahwa tak ada satupun negara di dunia kini yang layak disebut ‘republik.’ Karena Republik, sebagaimana digariskan Cicero, haruslah independen dalam pengaturan uang. Senat dan senator yang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengatur uang. Kini, era modern state, senat justru hanya menjadi ‘koeli-koeli’ oligarki bankir. Wujud senat, dan partai politik, hanya bekerja untuk kepentingan bankir. Dalam istilah lain, inilah taipan. Mereka yang mengatur dan menguasai sentra-pokok ‘state.’
Kondisi ini bukanlah barang baru dalam peradaban. Era Romawi, pernah mengalami hal serupa. Romawi, pasca Julius Caesar, mengalami penurunan dalam fase republik. Kemudian berubah menjadi tirani kerajaan. Senat tak lagi dominan, untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Kaisar, berubah menjadi boneka. “Itu berlangsung sejak era Augustinus sebagai Kaisar,” terang Ian Dallas. Kala itu, sambungnya, Kaisar berada di bawah kendali ‘Legiun.’ Ini tentara perang Romawi yang sangat disegani. “Kini Legiun digantikan oleh banker,” tukasnya. Era itulah yang disebut dengan ‘okhlokrasi’. Bukan lagi layak disebut demokrasi.
Merujuk siklus Polybios, sejarawan Romawi, maka fase pasca demokrasi, akan berubah menjadi okhlokrasi. Selepas itu, peradaban akan kembali menjadi monarkhi. Imperium banker ini tengah berada dalam keruntuhan. Karena banking system mengalami kelemahannya sendiri. Maka, bak perulangan siklus, fase okhlokrasi ini akan kembali kepada monarkhi. Dan, bentuk monarkhi terbaik adalah Madinah al Munawarah.
Monarkhi yang dimaksud tentu bukan bak ‘the king can do no wrong’ sebagaimana fitnah Thomas Hobbes. Melainkan tatanan pemerintahan dengan personal rule. Bukan system rule seperti era kini. Manusia menjalankan pola pemerintahan berlandaskan hokum Tuhan. Bukan lagi merujuk reason law. Tatanan monarkhi ini yang berlangsung pasca kehancuran Romawi barat. Karena kehancuran imperium bankir, telah diambang mata. Karena ‘head of state’ sejatinya tak memerintah. Senat tak mengatur. Politisi telah lumpuh. Karena tak mampu mengatur uang-nya sendiri.
Dari sini keruntuhan finansial system, akan mengiringi ‘the fall of state.’ Karena mimpi ‘the welfare state’ hanyalah bualan modernitas. Tapi realitasnya adalah kembali pada fitrah. Bankir telah membentuk ‘state’ menjadi boneka untuk mengeruk keuntungan semata. ‘Ration d’etat’ dipergunakan demi kepentingan ‘bankir corporation.’ Hubbal wathon minal iman, bukanlah mesti membela kepentingan ‘bankir corporation’ yang bersembunyi dibalik ‘liberte-egalite-fraternite.’ Melainkan harus kembali pada fitrahnya.
Islam telah memiliki pranata untuk memberikan jalan keluar. Itulah pola yang merujuk Amal Ahlul Madinah. Madinah al Munawarah. Kepemimpinan, yang sejatinya mengatur perihal ‘kehendak Tuhan’, termasuk dalam otoritas keuangan. Jalan keluar dari jerat imperium banker ini adalah keluar meninggalkannya. Kembali pada yang Haq, maka yang bathil musnah. Imperium banker ini menciptakan pranata banking system dan turunannya. Itulah system riba.
Keluar dari jerat system riba ini, dimulai dengan menegakkan kembali Zakat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahuwataala dalam Al Quran Surat Ar Rum. Ketika Zakat tegak, maka riba akan musnah. Insha Allah. Tegaknya Zakat, maka perlu Ulil Amri Minkum yang sejati. Bukan ‘pemimpin’ yang sejatinya tak berkuasa. Hilairre Belloc, sejarawan Inggris berkata, ‘Siapa mengendalilkan harta (uang), dialah penguasa.” Ketika ‘kurs uang’ dikendalikan bankir, maka merekalah sejatinya yang berkuasa. Maka, Ulil Amri Minkum harus kembali hadir di tengah umat, demi tegaknya rukun Zakat. Sebagaimana Sayidinna Abu Bakar as Shiddiq menjadikannya program utama kekhilafahan. Dari Zakat, maka akan lahir muamalah. Dari sanalah DIN Islam akan kembali menjawab masalah peradaban. Insha Allah.
Revolusi. Seolah ini solusi. Tapi revolusi tak semudah reformasi. Revolusi pertanda pergantian aqidah. Pergantian keyakinan. Karena revolusi bermakna pergantian system. Bukan sekedar berganti ‘supir.’ Curzio Malaparte, penulis ‘Technique Coup D’Etat,’ berkata, “Tak ada revolusi tanpa perpindahan property (kekayaan).” Dan itulah sejatinya revolusi.
Karena abad modern, revolusi menjadi titik pergantian kekuasaan. Revolusi Inggris, perpindahan kekayaan dari kaum Monarkhi menuju kaum bankir Yahudi. Sebelumnya, Monarkhi Inggris tunduk dibawah liga ‘Imperium Romanum Socrum.’ Dinasti Habsburg. Tapi merebaknya perang aqidah di Eropa, antara kelompok Gereja Roma dan Protestan, membuat Inggris kerajaan kedua yang dikuasai pengikut Luthern dan Calvinis. Setelah sebelumnya Kerajaan Belanda.
Revolusi Inggris terjadi setelah terjadinya perpindahan keyakinan. Inggris mengikut pada Pembaharuan Kristen. Disitulah Raja William dari Belanda, dinikahkan dengan Ratu Mary I. Pertanda Inggris telah masuk dalam cengekaraman aqidah baru. Tidak lagi merujuk pada kelompok Gereja Roma.
Edict of worm, menjadi pertanda munculnya revolusi di belantara Eropa. Tragedi pembantaian massal di Kerajaan Perancis, 1752, ‘Massace at Paris’ menjadi pemantik utama. Christopher Marlowe, menukiskan kisah ‘Massacre at Paris’ begitu mengerikan.
Pembantaian kaum Huguenot, yang dianggap pelaku bid’ah oleh fatwa ‘Edict of Worm.’ Ribuan Huguenot dibantai massal. Raja Charles hanya bak boneka tanpa memiliki kekuasaan penuh. Karena Ibunya, Chaterine de Medicie mengendalikan kerajaan sepenuhnya. Raja yang boneka, berakibat fatal pada rakyatnya. Karena Sang Ibu menghendaki kekuasaan harus tetap berada ditangan trah-nya. Munculnya aqidah baru, Pembaharu Kristen, dianggap mengancam kekuasaan Raja Perancis. Karena adagium Eropa kala itu, ‘Vox Rei Vox Dei.’ Suara Raja Suara Tuhan. Raja dianggap wakil Tuhan. Bak ‘umara’ dalam Islam.
Kerajaan Perancis, bersahabat erat dengan Daulah Ustamniyya. Koalisi Franco-Utsmani dikenal sepanjang massa. Pasca Crusaders, Perang Salib, Kerajaan Perancis tak lagi ikut berada dalam pasukan yang dibentuk Gereja Roma. Koalisi dagang dan pertahnanan, dipilih Perancis untuk eksistensi kerajaan.
Tapi merebaknya filsafat di Eropa, melahirkan renaissance, memunculkan geliat pemahaman baru atas tafsir agama Kristen. Renaissance menggoyang dogma Roma. Pra Renaissance, Eropa masih dilanda paham fatalism versi dogma. Raja dianggap wakil Tuhan. Melawan Raja dianggap melawan Tuhan. Tragedi Magna Charta, dimana Raja John berdamai dengan kaum Baron Inggris, dianggap sebagai penghinaan. Kelompok Roma menentang. ‘Tak sepatutnya Raja berdamai dengan rakyat.’ Tapi Magna Charta muncul berkat didikan Ordo Kesatria baru Eropa. Mereka hasil persinggungan antara kaum muslimin dan pasukan Salib pasca Crusaders. Perang berabad-abad itu, memantik terjadinya pertukaran budaya. Sultan Salahuddin al Ayyubi, mendidik para tawanan pasukan Eropa dengan mengembalikan sifat Ksatria. Ini yang disebut futtuwa. Mengembalikan etos Ksatria agar kembali menegakkan Kebenaran berlandaskan agama yang lurus. Dr. Ian Dallas menukiskan, dari situlah memunculkan Ordo Ksatria penjaga api suci Kristen. Yang mengamalkan ajaran Nasrani yang lurus. Hasilnya adalah melahirkan Dinasti Bourboun, yang mewarisi trah Kerajaan Inggris. Zuriyah itulah yang kemudian melahirkan trah Kerajaan Inggris, hingga melepaskan diri dari kelompok Imperium Romanum Socrum, liga kerajaan yang berada di bawah panji Gereja Roma.
Tapi disatu sisi, kelompok yang melawan Roma juga muncul dari filosof. Mereka mengambil ajaran mu’tazilah. Era ketika filsafat di Islam-kan. Renaissance, itu masa ketika filsafat ‘di-Kristen-kan.’ Para filosof kosmosentris ini ditentang habis Roma. Bruno dibakar, sampai Galileo dan Copernicus dihabisi. Pemikirannya ditentang. Sampai fisiknya pun dikejar. Sikap ekstrim menghadapi ajaran filsafat ini membuat kejumudan melanda Eropa. Walhasil melahirkan ‘paham’ baru ketertarikan Eropa pada ajaran filsafat.
Pasca ‘Massacre at Paris,’ pembantaian massal Huguenot, ajaran filsafat makin diminati. Karena dianggap ‘Raja’ bertindak lalim. ‘Apakah Tuhan menghendaki pembunuhan?’ Benarkah Raja adalah Wakil Tuhan?’ Segudang pertanyaan itu muncul berkaitan aqidah.
Merebaknya Francis Bacon, Rene Descartes, Immanuel Kant, dan lainnya, makin memantik bahwa aqidah Roma dianggap jumud. Descartes mengawali akrobatik. Mereka mendompleng ‘krisis kepercayaan’ atas dogma. Tapi para filosof materialistis membawa Eropa keluar meninggalkan hukum Tuhan. Cogito Ergo Sum bermakna, bahwa tak ada Kebenaran Wahyu. Yang dianggap ‘Kebenaran’ hanyalah yang bersumber dari yang bisa diserap inderawi manusia. Kant menihilkan lagi, karena ‘Kebenaran’ hanya sah jika melewati empirisme. Telah bias dibuktikan secara inderawi. Ajaran-ajaran inilah yang berkembang di Eropa. Alhasil makin melumpuhkan ajaran Roma. Walhasil pengikut penentang ‘Raja Wakil Tuhan’ pun makin mengecil. Dari filsafat, manusia diajarkan untuk ‘kehendak bebas (free will). Dari ajaran ‘free will’ inilah yang melahirkan free mason. Gerakan kebebasan. Humanisme menjadi pondasi utama.
Para pengikut ‘free will’ ini mengusung manusia itu dibekali kebebasan mutlak dalam alam dunia. Tuhan, kata filosof, telah memberikan akal pada manusia. Makanya manusia berhak mengungkap ‘being’ dengan akalnya. Ini sebagaimana ajaran Plato, Aristoteles perihal ‘theorie.’ Makanya Descartes berkata, filsafat adalah ajang dimana manusia, Tuhan, alam semesta menjadi ajang penyelidikan manusia. Materialisme memberikan ajaran, manusia sebagai subjek yang mengamati. Bukan lagi objek yang diamati. Free will. Inilah landasan sekulerisme, liberalisme sampai kapitalisme-positivisme. Secara umum, itulah modernisme. Babak baru peradaban Eropa modern.
Semangat free will tersebut melahirkan ‘Egalite-Liberte-Fraternite.’ Ini semboyan utama dalam Revolusi Perancis, 1879. Locus delict-nya berlangsung dititik yang sama ‘Massacre at Paris.’ Titiknya di Paris, Perancis. Masscare, kejadian kala kelompok Huguenot –pengikut Calvin dan Luthern–, dibantai. Sementara Revolusi Perancis, gantian pengikut Roma yang dibantai.
Tapi sebelum Revolusi dimulai, perang aqidah itu yang mewarnai.
Egalite, maknanya keadilan agar tidak lagi untuk pada ‘Kebenaran Wahyu.’ Melainkan hanya merujuk pada hokum reason. Hukum rasio manusia. Tak lagi percaya pada Kitab Suci. Liberte, merdeka dari belenggu agama. Karena manusia dibekali ‘kehendak bebas.’ Manusia berhak menentukan nasibnya sendiri. Tak lagi terbelenggu pada kejumudan agama.
Fraternite, persaudaraan sesama penganut paham ‘free will.’
Maka, lawan dari pengusung Revolusi Perancis adalah pengusung ‘Vox Rei Vox Dei.’ Mereka membaliknya menjadi ‘Vox Populi Vox Dei.’ Suara manusia, Suara Tuhan. Manusia dianggap memiliki kehendak bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Tak lagi merujuk Kitab Suci dan penafsir-tafsirnya.
Slogan ‘Vive Le Roi!’ (Hiduplah Raja!) yang kerap diteriakkan di istana Perancis, dikudeta menjadi ‘Vive le nation!’ Karena ‘ration d’Etat’ membahana. Beranjak dari ‘free will’, maka muncul ajaran teori baru perihal kekuasaan yang dihembuskan Machiavelli-Hobbes-sampai Rosseau. Mereka menegaskan bahwa manusia berhak memilih pemimpinnya sendiri. Tanpa harus taat pada Kebenaran Agama. Maka pasca Revolusi Perancis, melahirkan modern state dan mengenal ‘election’ (pemilihan umum). Pemimpin tak mesti keturunan atau titah dari agamawan. Melainkan harus dipilih berlandas kehendak manusia. Karena menganut paham ‘free will’ tadi.
Dibalik Revolusi Perancis, kaum ordo Bankir Yahudi ternyata menggeliat. Mereka kelompok yang sejak dulu memusuhi Gereja Roma. Karena kaum bankir ini menjalankan praktek riba, membungakan uang. Dulu mereka dilarang sejak era Isa Allaihissalam. Sampai masa Roma berkuasa, kaum Yahudi pedagang uang ini terus diburu. Tapi mereka berbisnis sembunyi-sembunyi.
Masa Revolusi Inggris tadi, kaum bankir ini kegirangan. Selepas Inggris lepas dari liga, Inggris kekurangan uang untuk mengelola kerajaan. Maka 25 bankir Yahudi membuat konsorsium untuk memberi utang kepada King William. Tapi dengan syarat, utang itu adalah berbunga. Dan King William wajib membayarkan setiap tahun dengan cicilan. Itulah ‘utang nasional’ pertama di dunia. Sebuah ‘state’ memiliki utang pada bankir. Pemberian utang itu, tak serta merta tanpa embel-embel. Bankir meminta jatah bahwa mereka yang mengatur ekonomi Inggris. Maka berdirinya ‘Bank of England.’ Bank sentral Inggris. Selepas Revolusi, William duduk jadi raja. Tapi telah menjadi boneka para bamkir. Karena dia tak sepenuhnya berkuasa. Bukan lagi monarkhi absolut. Melainkan monarkhi konstitusional. Karena kekuasaan raja dibatas. Dengan dalih atas nama: konstitusi.
Setahun kemudian, pola itu disebar ke Perancis. Rakyat didoktrin ‘liberte-egalite-fraternite.’ Seolah ini slogan ‘freedom.’ Padahal dibalik itu bankir Yahudi telah bersiap. Ketika Kerajaan Perancis berhasil menggulingkan King Louis XVI, maka kekuasaan jadi vakum. 75 Bankir membentuk konsorsium. Semua Robbiespierre, pemimpin revolusi, mengambil alih. Tapi kaum banker tak setuju dengannya. Dia dengan mudah dikudeta. Karena Robbiespierre tak memiliki kekayaan.
Bankir mendapuk Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar baru. Dia diberi modal para banker itu sejumlah 75 juta Franc. Tapi berbentuk utang berbunga. Sayarat serupa dengan Inggris tadi. Berdirinya ‘Bank de France,’ bank sentral Perancis. Napoleon jadi Kaisar, tapi punya utang yang harus dibayar.
Napoleon sadar dia hanya boneka banker. Dia melancarkan perang menganeksasi Etopa lainnya. Tapi dia kalah. Karena ambisi militer Napoleon, tak sejalan dengan ambisi bisnis para ordo bankir di Eropa. Perang Napoleon, tak menguntungkan secara bisnis. Dia pun dibuang ke Pulau Elba. Napoleon jelas bukanlah penguasa. Dia hanya boneka dari para ordo Bankir itu. Karena mereka yang sejatinya mengatur Republik Perancis baru. Produk dari revolusi.
Jadi, revolusi pertanda perpindahan kekuasan (power) dan kekayaan (wealth). Tak ada revolusi tanpa transfer of property. Pra revolusi, kekuasaan dan kekayaan dipegang kelompok Gereja Roma. Atas nama agama. Pasca revolusi, power and wealth pindah ke tangan ordo bankir. Atas nama ‘kehendak bebas manusia.’
Revolusi tentu harus berbasis aqidah. Tak ada revolusi hanya sebatas pergantian supir. Pergantian Robbiespierre ke Napoleon, itu tak dikata revolusi. Tapi Revolusi Perancis, menjadi titik tolak, bahwa aqidah menjadi mendahului revolusi.
Modernisme kini telah mencengkeram manusia. Utang nasional dialami semua state. Mulai Amerika sampai Kolombia. Tak ada modern state berada diluar control ordo bankir. Jalan revolusi, pertanda kembalinya pada aqidah yang benar. Karena banker akan langgeng dalam aqidah ‘free will.’ Antitesanya adalah paham ahlul Sunnah. Pasca Perancis dikooptasi, aqidah ‘free will’ merambah negeri-negeri Eropa. Kekuasaan Roma dihabisi. Kemudian setelah itu merambah negeri-negeri muslim. Daulah Utsmaniyya dikudeta, sampai kesultanan-kesultanan nusantara. Negeri muslim terimbas paham ‘free will’ yang melegenda. Maka antitesa ini hanya bisa dengan mengambalikan aqidah. Vox populi Vox Dei terbukti hanya slogan buatan kaum bankir untuk melanggengkan kekuasaannya. Tak ada kehendak rakyat berkuasa. Yang ada ‘pemerintahan dari bankir, oleh bankir dan untuk bankir.’ Bretton Wood, pasca Perang Dunia II menunjukkan kekuasaan mereka. Hanya kaum bankir yang bisa menunjukkan kepala-kepala negara.
Presiden Soeharto, yang gagah perkasa puluhan tahun, jatuh dengan mudah hanya dengan dilandasi oleh kurs uang. Karena tak ada satupun negara di dunia kini bisa mengendalikan uangnya sendiri. Kurs uang tak diatur oleh negara modern. Tapi berada ditangan kekuasaan bankir. Itulah sejatinya ‘power and wealth.’ Maka dengan mudah seorang Presiden dan PM dijatuhkan dan dinaikkan. Karena kekuasaan berada ditangan mereka. Dan mereka, kaum yang tak bernama. Tak dikenal nama, tapi produknya dimana-mana. Ordo banker inilah musuh umat manusia.
Maka, jalan kembali adalah jalan kala kita dikalahkan. Vox Rei Vox Dei, kembali jadi solusi. Ketika manusia harus memiliki pemimpinnya. Slogan itu diajarkan dalam Madinah Al Munawarah sampai Wali Songo di tanah Jawa. Manusia memerlukan pemimpin yang bisa lepas dari jerat bankir. Karena banker hidup dalam gumangan system riba. Kapitalisme.
Tak ada revolusi dari kaum sekuler kemudian pada sekuler lagi. Itu bukan revolusi. Melainkan hanya basa basi.
“Pra modern, Raja adalah wakil Tuhan. Modern state, presiden dianggap wakil rakyat. Post modern, pemimpin adalah wakil oligarkhi.”
King Louis XVI sesosok muda penuh makna. Dia raja Perancis terakhir. Nasibnya digantung di depan penjara Bastille. Perang aqidah membahana berabad-abad sebelumnya. Antara pengikut ‘kehendak Tuhan’ atau ‘kehendak manusia.’ Tahun 1789 itu, revolusi Perancis pecah di Paris. Pengikut ‘kehendak manusia’ memenangkan massa. Mereka melakukan revolusi besar. Robiespierre pemimpin kaum pengusung ‘kehendak manusia.’ Mereka meneriakkan slogan ‘Liberte, Egalite, Fraternite’ dimana-mana. Liberte, merdeka dari urusan ‘kehendak Tuhan.’ Egalite, bermakna keadilan hukum yang harus dibuat berlandas ‘kehendak manusia.’ Fraternite, persaudaraan sesame pengikut ‘kehendak manusia.’ Revolusi Perancis adalah perang antara dua pengikut aliran itu. Tapi kaum pengusung ‘kehendak manusia’ sebagai pemenang.
Robiespierre tentu merujuk kitab sucinya, buku JJ Rousseau. Dia menafsirkan ‘kehendak manusia’ itu sebagai ‘kehendak rakyat.’ Manusia yang berhak menentukan siapa pemimpinnya. Bukan lagi berlandas ‘wakil Tuhan’ yang merujuk pada ‘kehendak Tuhan.’ Pra revolusi itu, Eropa dilanda dogma ‘Vox Rei Vox Dei.’ Suara Raja Suara Tuhan. Ini yang kemudian dikudeta menjadi ‘Vox Populi Vox Dei.” Suara rakyat, suara Tuhan. Dua adagium itu, pertarungan perihal aqidah. Antara pengikut jabariyya melawan qadariyya. Mereka perang betulan di Paris. Tapi Revolusi Perancis itu, pembantaian pengikut ‘kehendak Tuhan’ oleh kaum fanatik pada paham ‘kehendak manusia.’
Raja Louis XVI, simbolisasi pengikut ‘kehendak Tuhan.’ Begitu selepas digantung di depan Bastille, kepalanya dipenggal dan ditenteng sepanjang jalan Paris. Robiespierre berkata, “Inikah wakil Tuhan itu?” Pertanda Raja bukanlah ‘wakil Tuhan.’ Kalimat Robiespierre itu yang ditiru Kemal Attaturk seabad kemudian. Kala menggulingkan Daulah Utsmaniyya dan mengubah menjadi Republik Turki. Landasan semangatnya sama: pengusung ‘kehendak manusia.’ Selepas menggulingkan Sultan Abdul Hamid II sebagai Sultan Utsmaniyya, Attaturk berpidato keras, “Sekarang kehendak siapa yang berkuasa? Kehendak Tuhan atau kehendak saya?” Gemuruh kaum ‘young Turks’ menyambutnya. Mereka para modernis Islam. Kaum yang ingin duduk sejajar dengan kuffar.
Perihal aqidah ini memang tak biasa. Revolusi Perancis jadi ajang persekusi dan eksekusi. Paris banjir darah. Hanya perbedaan tafsir perihal ‘kehendak.’ Pengusung revolusi, tentu pengikut ‘free will.’ Mereka menafsirkan ‘segala sesuatunya adalah materi.’ Ini bermula dari ajaran filsafat. Robiespierre hanya anak kandung dari ideologi ‘Robiespierre.’ Dan Robiespierre merupakan anak ideologis dari Jean Bodin. Dia pengusung ‘modern state’ bahwa manusia yang berhak menentukan pemimpinnya. Kekuasaan adalah buah dari ‘kehendak manusia.’ Bodin tentu berada dalam satu millah yang sama dengan Montesquei, Machiavelli, sampai Thomas Hobbes. Mereka inilah pengusung aliran ‘politique’ yang berkembang abad pertengahan di Eropa.
Politiue (politik) ini yang bergema dalam sisi kekuasaan. Buah dari ajaran filsafat. Karena Rene Descartes telah mendeklarasikan ‘cogito ergo sum.’ Manusia sebagai subjek yang mengamati. Manusia bukan objek yang diamati. Jadi manusia sebagai penentu. Descartes berkata, “filsafat adalah ajang dimana manusia, Tuhan, alam semesta dan lainnya menjadi ajang penyelidikan manusia.’ Dari sinilah pemisahan antara akal dan wahyu. Karena Cartesian memberi tunjuk ajar, manusia sebagai sentral point atas segalanya. Mereka menafsirkan ‘idea’- Plato kebablasan. Idea itulah sumber utama untuk menentukan siapa yang berhak sebagai penguasa.
Dogma Gereja Roma, yang hidup abad pertengahan, memberi ajaran bahwa kekuasaan adalah wakil Tuhan. Roma sebagai entitas yang berhak menafsirkan kitab suci. Maka, Raja-Raja haruslah yang mendapat restu dan petunjuk dari Roma. Era itulah Gereja Roma menjadi pusat utama kekuasaan. Karena dalam dinamika itu Raja ditentukan. Sehingga adagium ‘the king can do no wrong’ membahana. Perintah Raja, dianggap perintah Tuhan. Tapi berabad-abad, banyak praktek kerajaan yang keluar dari rasionalitas. Disinilah pengusung filsafat masuk menusuk mulai mencari tanya. “Benarkah raja wakil Tuhan? Jika raja salah, apa itu merupakan kehendak Tuhan?”
Serangan perihal aqidah dari John Calvin dan Luthern menjadi mencuat tajam. Otoritas Roma makin terdegradasi perlahan. Massacre de Paris, 1572, menjadi ajang pembantaian awal dua pengikut. Karena Roma memberikan titah tegas, pengikut Calvin, Huguenot, itu dicap sebagai bid’ah. Dan bid’ah dibolehkan dibunuh. King Charles IX, Raja Perancis, mengikut titah itu. Tapi peristiwa itu dijadikan ajang menyingkirkan pesainya. Karena ibunya King Charles, Chaterine de Medicie, terlalu dominan mengendalikan kerajaan. Disitulah bentuk kerajaan yang tak sehat. Karena Raja tak memimpin.
‘Massacre de Paris’ itulah ajang pembunuhan besar-besaran atas nama aqidah. Dupplesis Mornay, penasehat kerajaan Perancis, mencatatkan dalam dramanya. Peristiwa kelam pembantaian perihal perbedaan cara pandang terhadap Tuhan.
Pasca “Massacre de Paris’ itulah mencuat dua aliran pemikiran. Pengusung “politque” dan pengusung ‘monarchomach’. Ini dua aliran berbeda. Machiavelli dan turunannya tentu lebih memilih bahwa tafsir atas ‘kekuasaan’ harus diteorikan ulang. Tapi kaum Monarchomach tak begitu. Mereka tetap mengusung kekuasaan adalah ‘kehendak Tuhan.’ Tapi mereka anti monarkhi. Tak setuju dengan praktek kerajaan yang berlangsung di Eropa. Mereka juga menolak ‘the king can do no wrong.’
Bagaimana jika raja melakukan kesalahan? Kaum monarchomachen meniru praktek kekuasaan Romawi kuno. Kala Julius Caesar dianggap melakukan corrupt pada Republik Romawi. 29 Senator berkumpul dalam konspirasi. Mereka melakukan pembunuhan Caesar dalam Senat. Itulah jalan Monarchomach. Raja lalim, bisa dipenggal. Raja berbuat salah, bisa diganti. Tapi peranan Senat haruslah dominan. Masa Romawi. Senat bukan diisi sembarang orang. Bukan dilotere, bak era kini. Melainkan Senat haruslah cerdik pandai, alim ulama. Mereka penyambung lidah rakyat. Demokrasi modern, hanya bak “fiction telling” –seperti kata Ian Dallas–, ulama besar dari Eropa. Karena demokrasi modern, bukanlah demokrasi.
Tapi aliran Monarchomach ini kala tenar dengan pengusung ‘politique.’ Teori Bodin, Hobbes, sampai Rousseaou lebih diminati. Karena persolan tafsir ‘kehendak siapa’ ini menjadi membuncah tajam. Serangan filsafat di Eropa, tak bisa dibendung kaum alim ulama Gereja Roma. Mereka sering menyikapinya bukan dengan ilmiah. Gelileo dihukum, Bruno dibakar sampai filosof dikejar-kejar, pertanda itulah akhir dari peradabannya. Era kini berbalik. Pengusung filsafat berubah menjadi anakhis.
Ini yang bisa dilihat pasca Revolusi Perancis. Pengikut ‘kehendak manusia’ berubah menjadi anakhisme. People power digunakan menggulingkan titah Kerajaan dan Gereja Roma. Tapi setelah itu, perubahan drastis terjadi. Jika sebelum Revolusi, Eropa terbagi dalam tiga kelas. Kelas pertama, kaum bangsawan dan agamawan. Kelas kedua, kaum borjuis, para baron. Kelas ketiga, kaum proletar. Rakyat.
Pasca revolusi, kelas bangsawan dan agamawan disingkirkan. Kaum borjuis dan para baron mengambil alih. Mereka menjadi strata teratas. Dan kaum proletar, tetap pada kelasnya. Tak ada kelas kedua.
Robiespierre tak menyadari itu. Dikiranya ‘kehendak manusia’ akan menyelesaikan masalah. Pasca dia memenggal kepala Louis XVI, dikiranya dia adalah Pemimpin Republik Perancis. Beberapa tahun dia bertatha, dia dikudeta. Napoleon didapuk menjadi Kaisar baru. Siapa mengkudeta Robiespierre? Mereka-lah kelompok kelas baru: kaum borjuis dan baron. Mereka yang kemudian mengambil alih kekuasaan secara de facto. Para borjuis, berkumpul menentukan Napoleon sebagai Kaisar. Mereka kemudian memberi Napoleon pinjaman uang berbunga sebesar 75 Juta Franc. Itu dianggap utang nasional. Tapi para borjuis itu menuntut hak untuk mengatur ekonomi Perancis baru. Mereka membentuk ‘Bank de France.’ Inilah bank nasional Perancis. Napoleon wajib membayar utang berbunga setiap tahun. Dia Kaisar, tapi tak berkuasa atas keuangan Perancis.
Stendhal, pakar sejarah Inggris berkata, “Penguasa adalah dia yang mengendalikan harta.” Tragedi Napoleon menjadi bukti, dia sebagai Kaisar hanya boneka. Terbukti, beberapa tahun kemudian dia dibuang ke Pulau Elba. Napoleon merana. Nasibnya tak berbeda jauh dengan Robiespierre. Kaisar berganti, Presiden berganti, tapi kekuasaan tetap dipegang kaum borjuis tadi. Merekalah oligarkhi.
Kekuaan para oligarkhi ini Nampak pasca Perang Dunia II. Mereka mengumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin negara. Tak ada namanya negara adidaya. Bretton Wood, 1944, jadi bukti siapa yang bisa memerintah negara-negara. Mereka berkata, “Mulai sekarang kami menerbitkan uang tak ada lagi back up emas.” Itu pertanda kekuasaan oligarkhi tak bisa dibantah. Tak ada satu head of state-pun bisa membantah. “Siapa saja boleh jadi presiden, asal kami yang mencetak uangnya,” kata Rotschild.
Tentu perpanjangan tangan kaum oligarkhi tadi adalah system rule. Mereka membuat system yang harus dipatuhi. Disitulah mereka berlindung pada positivism. Ini aliran hukum untuk menterjemahkan “kehendak manusia.” Dan mereka memanfaatkan ‘kehendak manusia’ dalam politique. Karena dengan begitu, mereka bisa menentukan sesiapa presiden yang dikehendaki.
Demokrasi modern, mereka berperan bak ‘ahlul halli wal aqdi.’ Yang menentukan sesiapa pemimpin di sebuah negara. Disinilah esoterisme terjadi. Tentu ini buah adagium ‘segala sesuatunya adalah materi.’ Karena percaya pada doktrin itu, seolah manusia memiliki ‘kehendak bebas.’ Termasuk ‘kehendak bebas’ dalam memilih pemimpin. Dari ‘kehendak bebas’ itulah oligarkhi telah mengunci dalam system-nya.
Tentu jalan keluar dari ‘lubang biyawak’ ini bukan mengikutinya. Melainkan keluar dari lubang. Islam memiliki pranata lengkap perihalnya. Bagaimana memilih pemimpin, ditentukan kaum alim ulama. Ahlul Halli wal aqdi. Wali Songo mempraktekkannya dalam menentukan Raden Fatah sebagai Sultan Demak. Utsmaniyya menjalankannya berabad-abad. Para ulama berada digaris depan pemerintahan. Pemimpin bukan dilotere, yang pemenangkan telah dikantongi oligarkhi sejak mula. Sementara massa, hanya disibukkan urusan simbolisasi dan psy war, yang seolah itulah dinamika. Padahal, tak bisa seorang calon tanpa peranan oligarkhi. Karena demokrasi modern berubah menjadi industry. Perlu modal dan capital. Ini tentu bukan lagi layak disebut demokrasi. Merujuk siklus Polybios, sejarawan Romawi, fase ini telah berada dalam okhlokrasi.
Romawi dulu pernah berada dalam fase okhlokrasi. Kala Kaisar dikendalikan sepenuhnya oleh Legiun. Sekelompok militer. Kini, pemimpin dikendalikan kaum elit oligarkhi bankir. Tapi, pasca fase okhlokrasi, maka akan kembali ke monarkhi. Tentu bukan monarkhi yang “the king can do no wrong.” Melainkan bak Madinah Al Munawarah. Pemimpin yang merujuk pada ‘Kehendak Tuhan.’ Tentu berada dalam jamaah yang tak mengusung aliran ‘qadariyya.’ Inilah jalan keluar dari lubang biawak. Karena perihal kepemimpinan, disitu pula urusan Tauhidullah.
Tersebutlah nama Plato. Filosof Yunani kuno dengan kitabnya, Republik. Ini ‘idea’ Plato tentang sebuah kota yang ideal. Plato mensandarkannya pada pemahaman manusia yang harus merujuk filsafat. Cara berpikir rasio. Bahasa lainnya, logika. Logos. Dalam makna luas, ini diartikan sebagai akal. Plato menyebut, sebuah kota yang ideal jika masyarakatnya jamak menggunakan cara berpikir rasionalitas. Akal budi. Tapi lihat masa kala Plato menyusun republik. Manusia jamak dipenuhi penyembahan pada bintang, bulan, matahari yang dianggap dewa. Itu yang disembah. Plato tak menyetujuinya. Dari gurunya, pemikir corrupting the youth, Socrates. Plato meneruskan metode berpikir rasio. Jadilah utopia-nya tentang ‘Republik’. Kata yang bersalah dari ‘res’ dan ‘publica’. Maknanya “urusan umum.” Kekuasaan yang dipegang oleh masyarakat banyak. Bukan penguasa yang mengendalikan dogma.
Dari Plato, republik sempat menyambar Cicero. Ini masa Romawi kuno. Masa Julius Caesar mengagungkan Romawi. Ini jaman kejayaan kaum Eropa. Tapi Al Qur’an mendudukkannya khusus dengan nama sebuah ayat: AR RUM. Pertanda Romawi memang bukan peradaban sembarangan. Karena sekuelnya panjang. Dari Romawi ber-Tauhid hingga Romawi pagan. Dari Romawi masa didirikan Romulus dengan Tauhid, hingga berakhir pada paganisme, bak masa Plato. Cicero mengingatkan lagi tentang ‘republik.’ Urusan umum. Sebuah tatanan peradaban yang berpatokan pada kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Tapi maknanya bukan semata demokrasi. Melainkan juga berbentuk monarkhi atau pun aristokrasi. Ketiga format itu, monarkhi, aristokrasi, demokrasi, layak dicap sebagai format ‘republik’. Cicero mengingatkan lagi Romawi. Persis pasca tragedi pembunuhan Julis Caesar oleh Brutus, Romawi menurun tajam. Republik ala Romawi mulai turun drastis. Berganti menjadi tirani. Dalam format Polybios, disebut okhlokrasi. Bukan lagi menjalankan demokrasi. Karena kaisar Romawi tak lagi memerintah demi urusan rakyat. Melainkan di bawah kontrol Legiun Romawi. Pasukan kesatria (kini disebut tentara), mengontrol Kaisar Romawi. Fase ini dimulai sejak jaman Augustus. Masa itulah republik mati suri. Peradaban masih bernama Romawi. Tapi bukan lagi republik. Peringatan Cicero tak dijamah. Tapi Cicero menceritakan republik tak sama dengan Plato. Karena Cicero menjelaskannya dengan ‘Divine Law’. Bukan republik yang reason law. Di sini tampak beda Cicero dengan Plato.
Masa Islam datang, Madinah al Munawarah menjadi patokan. Rasulullah Shallahuallaihi wassalam telah meletakkan. Tata pemerintahan Islam yang sempurna. Dengan hukum yang bukan rasionalitas. Melainkan kategori ‘natural law’. Inilah format ideal dalam membangun kota peradaban. Dengan Tauhid yang terjamin. Masyarakat ideal, dari Madinah hingga masa Khulafaur Rasyidin. Diteruskan hingga era Ummayah, Abbasiyya bahkan Utsmaniyya. Dan merambah wilayah Melayu dengan kesultanan. Inilah format ideal tata pemerintahan.
Tapi di pertengahan, Islam terambah cara berpikir gaya Plato. Rasionalitas muncul kembali. Fase ini yang disebut jaman mu’tazilah. Qadariyya. Cara memahami Islam dengan filsafat. Muncullah Al Farabi, 894 Masehi. Mengembalikan lagi Plato. Dia meluncurkan kitab ‘Al Madinatul Fadhilah’. Jamak diterjemahkan ‘kota utama’. Ada juga mengistilahkan ‘negara utama’. Tentu padanan yang tak sama. Jauh berbeda. Al Madinatul Fadhilah, risalah Al Farabi tentang format ideal tata pemerintahan yang harus diisi dengan filosof. Karena mereka dianggap memiliki kemampuan sama seperti Nabi, dalam memahami Wahyu. Bedanya, seperti kata Ibnu Sina, Nabi mendapat Wahyu dengan pemberian langsung dan ketinggian intelektual. Filosof memahami Wahyu dengan pengalaman dan hasil penelitian akal. Masa itulah mu’tazilah menggaungkan Islam dengan sains-nya. Tapi kemudian diberangus dengan kembalinya tassawuf. Bentuknya adalah masa Salahuddin hingga Utsmaniyya. yang berdiri kembali bak Madinah al Munawarah. Al Madinatul Fadhillah, tak beda dengan konsep Plato, republik yang dianggap utopia.
Tapi rasionalitas dipungut Eropa. Filsafat digunakan untuk melawan kediktatoran Gereja Roma. Dari sanalah rennaisance menggema. Filsafat menggema di Eropa hingga melahirkan modernisme. Positivisme. Jauh melampaui kaum mu’tazilah. Karena rennaisance melahirkan ‘tuhan’ yang bukan Tuhan. Humanisme sampai simbolisasi lainnya tentang format kekuasaan. Filsafat telah melebar terlalu jauh. Alhasil melahirkan banyak problematika jaman.
Dari sinilah patut melongok ‘The Entire City’. Kitab penting yang ditulis terakhir DR. Ian Dallas. Nama beliau yang lain ialah Shaykh Abdalqadir as sufi. Gelar ‘as sufi’ menunjuk beliau seorang sufi, bukan rasionalitas. Masa mu’tazilah, banyak berbangga melekatkan nama belakangnya sebagai ‘al mu’tazili’. Ian Dallas berbeda. Dia lahir di Eropa, tempat rennaisance digodok dan melahirkan formatnya.
Isi The Entire City berisi tiga bagian. Tentang outward, inward dan the hidden. Yang tampak, inilah yang dirasakan manusia modern. Tentang humanisme, hasil produk rennaisance tadi. Yang puncaknya melahirkan ‘state’ (negara). Dallas menggunakan artikel Harold Laski, lawyer Inggris abad 20. Dia menuliskan tentang ‘Vindiciae Contra Tyrannos’. Perlawanan pada tirani kekuasaan. Masa modern, manusia jamak tak memahami apa dan bagaimana bentuk tirani. Tentu jelas bukan ‘republik’. Dari Laski kita bisa memahami. Tapi tunggu. Karena Laski membawa kita pada abad pertengahan. Tatkala penggodokan modernitas terjadi. Laski mengutip artikel panjang Dupplesis Mornay. Beliau yang memperjuangkan monarchomach (anti monarkhi). Ini sekuel masa itu. Kala Eropa dilanda rennaisance. Kekuasaan dipegang kendali Raja dan Gereja. Atas nama monarkhi. Tapi yang berlangsung bukanlah ‘republik.’ Melainkan dogma yang kemudian menjadi tirani.
Dari naskah Mornay, kita bisa mahfum terjadinya pertarungan dua aliran pemikiran. Monarchomach dan politics. Karena teori tentang kekuasaan tengah dibahas. Seiring merebaknya filsafat di Eropa. Revolusi sains mendorong ketertarikan Eropa pada filsafat. Warisan mu’tazilah. Dari sanalah mereka bertemu Socrates sampai Aristoteles. Sementara belantara Islam meninggalkannya. Kembali pada Madinah al Munawarah.
Eropa merancang format baru kekuasaan. Aliran politics, dimulai dari Machiavelli. Dia melontorkan kalimat baru, “lo stato’, yang tak pernah dikenal sebelumnya. Ini yang kemudian diterjemahkan menjadi ‘state’. Machiavelli berteori kekuasaan harus mampu bertindak bengis. Penguasa harus cerdik bak kancil, dan buas bak harimau. Agar memiliki kewibawaan. Teori Machiavelli diteruskan Montesquei. Kekuasaan harus dijalankan perimbangan, pengawasan. Inilah lahir Trias Politica. Lalu berlanjut pada Jean Bodin. Tentang teori soverignity. Kedaulatan. Hingga melahirkan John Locke sampai Hobbes dengan Leviathan. Absolute power harus ditangan rakyat sebagai penentu. Ingat, masa itu adagiumnya ‘Vox Rei vox Dei’ (suara Raja suara Tuhan). Lalu berujung pada Rosseou, yang membolak balik teori absolute power hanya berada pada rakyat. Bukan lagi berada pada Tuhan. Nah, inilah kreasi dari filsafat. Yang berbentuk humanisme. Manusia yang memegang kendali urusan dunia. Karena Tuhan didudukkan seolah bak pembuat jam. Kala jam selesai dibuat, maka akan berjalan dengan sendirinya.
Dari Rosseou itulah konsep ‘state’ dimatangkan dengan ‘Le contract sociale’. Revolusi Perancis, 1789, menjadi babak baru dimulainya ‘state’. Yang kini diwarisi tanpa ada lagi perdebatan. Padahal Mornay melakukan perlawanan. Lewat ‘Vindiciae Contra Tyrannos’, Mornay menjabarkan tentang monarchomach. Yang merujuk pada kekuasaan fitrah. Eropa mengenalnya dengan ‘virtue’. Romawi pun menggunakannya. Tapi Machiavelli menggeser makna ‘virtue’ itu dengan defenisinya sendiri. Namun Mornay memberikan kita, manusia masa modern, sebuah catatan. Bahwa teori ‘politics’ tidaklah satu-satunya yang dulu pernah ada dalam perihal kekuasaan. Karena Dallas menyebutkan, ‘politik itu menghancurkan taqwa.” Ini state itulah bentuk nyatanya. Kedaulatan Tuhan dipangkas. Bersisa pada kedaulatan rakyat semata. Merujuk pada Rosseou. Dari situlah Laski memberikan kesimpulan. Lawyer Inggris itu menukiskan tegas, perlunya re-evaluasi pada konsep ‘state’. Seperti yang dikata juga oleh Mornay. Nah, bagian inilah yang kategori outward.
Lalu masuk lebih dalam. Tentang bagaimana watak manusia yang berada di dalam kungkungan pola itu. Dallas menyuguhkan kisah ‘Masacre de Paris’, peristiwa besar abad pertengahan di kerajaan Perancis. Kala Louis IX menjadi Raja. Tapi bukan memerintah. Melainkan menjadi boneka. Dikendalikan ibunya, Caterine de Medici. Tentang kekuasaan yang dibawah kontrol pihak lain. Bukan ditangannya. Inilah format state kini. Karena kedaulatan bukan berada pada penguasa, yang disebutkan penguasa. Drama ‘masacre de paris’ sekuel tentang pembantaian Huguenot di Kerajaan Perancis. Tatkala kaum Protestan berusaha mendobrak tirani Gereja Roma. Raja digunakan untuk meneruskan ambisi kekuasaan. Ada berbagai pihak terlibat. Ibunya, sang pengendali, dan Gereja sebagai pemegang otoritas kekayaan masa itu. Jadilah peristiwa beradarah. Huguenot dibantai malam hari dengan racun, dalam perayaan peringatan Santo Bartolomeus, sahabat Isa Allaihisalam yang dibunuh penguasa Romawi dulu.
Watak ‘Masacre de Paris’ terus hidup masa kini. Masa modern, yang dianggap kemajuan. Tapi justru itulah hantu bertajuk humanisme. Karena pembataian terjadi kapan saja. Atas nama kekuasaan yang bukan fitrah. Inilah wajah modernitas kini. Wajah state sebagai format kekuasaan sekarang.
Dari situlah Dallas menyebutkan, “Kini tak ada satu negara (state) pun yang pantas disebut sebagai republik.” Mengapa Dallas berkata demikian? Kembali rujuk Republik Plato maupun Cicero. Konsep yang dulu dijalankan Romawi. Republik adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dallas telah membuktikan, kekuasaan kini bukan berada di tangan ‘state’. Melainkan di bawah kendali bankir. Bak Raja Louis IX, dibawah kendali Caterine de Medici. Bak Kaisar Augustus di bawah kontrol Legiun Romawi. Kini ‘state’ di bawah kontrol bankir. Perulangan yang terjadi. Dari situ, patutlah disimak apa pesan Dallas. Bahwa kini memang bukan masa republik. Melainkan perulangan periode Augustus, kaisar Romawi yang dibawah kontrol. Tentu ini bukan format Madinah al Munawarah. Ini bukan kota ideal. Apalagi kota utama.
Di bagian akhir bukunya, Dallas memberikan kata kunci. Kemusyrikan. Inilah bentuk yang melanda kota-kota kini. Karena kemusyrikan itu telah membuat manusia modern menjadi ‘manusia burung’ yang ketakutan. Digambarkan Dallas dengan meletakkan lukisan Max Ernst berjudul ‘The Entire City.’ Tapi kemusyrikan itu harus dilawan. Dallas memberikan Al Quran surat Al Kahfi. Tentang kisah pemuda Kahfi yang melawan kemusyrikan yang melanda kota-nya. Dari sana mereka berkumpul menjadi satu dalam goa. Dan membentuk peradaban baru.
Dari situlah tercipta ‘The Entire City’. Kota yang sempurna. Madinah al Munawarah. Kota yang fitrah. Seperti kata Cicero, dengan Divine Law di dalamnya. Karena republik, pertanda kekuasaan dan kekayaan berada pada satu tangan. Personal rule. Model kini, bukan layak disebut republik. Kekayaan di bawah kendali bankir. Dan ‘state’ hanya menjadi boneka bankir. Dari sini patutlah layak melongok lagi seperti kata Laski tadi.
Dallas membuka awal dengan artikel Laski. Ini ketua Partai Buruh di Inggris, abad 20. Dallas pernah menemuinya sekali, selagi muda. Maklum, Dallas juga besar dan tumbuh di negeri itu. Dia masuk Islam di usia 30-an di negeri Magribi. Dia memasuki Islam dan mendalami sufi. Hingga menjadi Mursyid dan kembali ke belantara Eropa. Membawa banyak manusia memasuki Islam, dan kini muridnya tersebar lebar seantero dunia.
Kembali ke The Entire City. Bekal itulah Dallas mampu membimbing kita dengan bukunya. Memberi tunjuk ajar tentang bagaimana suatu yang fitrah. Yang semestinya manusia lakukan, bukan mengikuti poros setan (axis of evil).
Dallas mengutip kalimat Laski. Tentang ‘state” atau ‘negara’. Terjemahan yang tak pas tentunya. Laski mendedah tentang makhluk bernama ‘state’ yang dulunya simbol atas kemerdekaan. Kini state berdiri gagah dimana-mana. Lambang kemerdekaan. Tapi Laski berkata, “the ultimate implication of the monistic state in a society so complex as our own is the transference of freedom ordinary men to their rules.”
Dari sini kita paham, state yang dulunya wadah menuju freedom, ternyata bukanlah freedom. Dallas menggunakan Laski untuk mengatakan bahwa state kini telah berubah menjadi tiran. Bukan wadah kebebasan. Karena Laski menggunakan lagi artikel yang ditulis Dupllesis Mornay, abad 16, berjudul vinidiciae contra tyranoss. Inilah artikel yang menggelegar di abad pertengahan, symbol perlawanan pada kaum raja dan Gereja kala itu. Yang dianggap telah berubah menjadi tiran.
Dari Laski kita terbang jauh ke abad pertengahan, Mornay. Dia penulis beraliran monarchomach. Anti Monarkhi. Mornay, penasehat Raja Charles di Perancis, yang selamat dari peristiwa pembantaian dalam kejadian peringatan Santo Bartolomeus, sahabat Isa Allaihisalam yang dibantai kaum Romawi. Para Nasrani memperingati hari pembantaian itu saban tahun. Masa itu, Eropa berada dalam situasi ‘Vox Rei Vox Dei’ (Suara Raja Suara Tuhan). Kedaulatan berada di tangan raja, yang dianggap perwakilan Tuhan.
Eropa berada dalam Imperium Romanum Socrum (IRS) yang di bawahnya para monarkhi-monarkhi. Tapi bentuk pemerintahan telah berjalan tak merujuk lagi fitrah. Melainkan merambah pada tiran, yang berbentuk penindasan. Perlawanan datang dari warga kelas dua: borjuis atau baron. Magna Charta di Inggris, abad 13, pertanda dimulainya kemenangan kaum baron atas kedigdayaan Raja, wakil Tuhan. Itu pertanda secara politik, raja tak sepenuhnya benar. Karena adagium kala itu ‘the king can do no wrong’. Magna Charta menanam benih perlawanan.
Pembahasan soal kekuasaan pun merambah. Ditambah gairah kehidupan hukum tak berlogika, Dallas mengutip Holmes, yang telah ada di belantara Eropa sebelumnya. Masa Romawi yang menanggalkan virtue (futtuwa). Maka, pertarungan abad pertengahan, seiring munculnya Protestan, perang aqidah tak terhindarkan. Perang itu merambah soal defenisi kekuasaan. Laski mengutip Mornay, mengatakan: ‘Pertumbuhan nasionalisme di abad ke lima belas dan enam belas telah menyiapkan landasan untuk desentralisasin kekuasaan agama…” Hasrat pertarungan kaum rasionalis (skolastik) dan tradisionalis makin kencang. Tapi minat Eropa makin condong pada rasionalis. Ini yang telah dimulai dari merebaknya filsafat, yang semula hanya mengulas soal kosmosentris. Soal kekuasaan pun mulai menjadi ajang pemikiran rasio manusia. Disitulah mulai dari Machiavelli, Montesquei, sampai Rosseou, berlomba mengeluarkan akrobatik pemikiran perihal bentuk kekuasaan. Bentuk makhluk baru bernama ‘state’ pun dimunculkan. Sebagai antitesa dari kekuasaan yang tak lagi fitrah. Raja dan kerajaan. Vindiciae menjadi ajang perlawanan atas kekuasaan unfitrah, yang telah ditunjukkan dalam peristiwa pembantaian 1000 lebih Huguenot di kerajaan Perancis. Dengan dalang Chaterine de Medici, seorang perempuan yang ambisi atas kekuasaan tahta Raja Perancis. Inilah watak sejati kekuasaan yang dipenuhi nafsu.
Dari artikel vindiciae ala Mornay, Laski ingin mendedah kekuasaan yang berlangsung tiran, masa abad pertengahan. Hingga memunculkan sekuel baru masa modern. Itulah ‘state’ menjadi wujud, dan menjadi bentuk hasil rasio manusia. Tapi melalui Laski, Dallas ingin mengatakan, kita patut untuk me-re-evaluasi bentuk state, yang juga tirani masa kini. Inilah pesan utama yang ingin disampaikan sang author di bab itu.
Lalu beliau membeberkan tentang kisah Massacre de Paris, yang ditunjukkan Marlowe. Tentang watak kekuasaan yang tak fitrah. Ini kisah drama yang berlangsung di istana Raja Perancis. Tentang sekuel permainan dan drama seharian, penguasa yang telah penuh nafsu. Sekuel tipu daya, saling makan, bak orang kesurupan, ditunjukkan dalam drama Marlowe itu. Pembaca buku ini akan terbawa untuk terpanpang perangai penguasa yang dipenuhi ambisi akan tahta. Dari Marlowe, kita bisa membaca kekuasaan unfitrah tak seenak kelihatannya.
Tapi sebelum itu, Dallas membawa kita kembali dulu ke masa Romawi. Kala terjadi pembunuhan Julis Caesar di depan senator. Peristiwa yang digambarkan Cicero, sebagai bentuk pelampiasan hawa nafsu setan. Cicero sangat menentang pembunuhan Caesar. Cicero menyerang Brutus dalam kisah artikelnya. Ini watak serupa tentang kekuasaan yang penuh ambisi. Dari kejadian Romawi itu, Dallas berani mengatakan, masa republik Romawi telah berakhir. Karena Republik, sejatinya sebuah sistem pemerintahan yang fitrah. Dengan pola hukum Tuhan.
Terbunuhnya Caesar, bentuk penurunan masa republik di Romawi.
Sekuel ini terus bersambung. Rangkaian peristiwa sejarah dunia ditunjukkan dalam The Entire City. Tentang jatuh bangunnya kekuasaan yang penuh virtue atau sebaliknya. Ini kitab panjang tentang jaman. Yang bagian akhir mendedah tentang jalan keluar menghadapi tirani masa kini: state tadi.
Tentu ini bukan sajian tentang perjanalan Ian Dallas. Apalagi kisah biographinya. Apalagi hanya berpesan soal pengungkapan soal qalbu. Tapi banyak pesan-pesan mendalam tentang perjalanan bentuk dan sistem pemerintahan yang berada dalam siklus.
Karena Dallas menyajikan Polibios dan Khaldun sebagai rujukan perjalanan siklus jaman. Ini patut disimak, karena kita berada masa interim,. Masa perpindahan dari pola okhokrasi menuju monarkhi, sistem yang kembali merujuk fitrah. Inilah pesan utama. Bahwa kita harus bersiap menyambut masa interim. Mempersiapkan kembali berjamaah dengan asyabiyya yang berisikan kaum futtuwa. Bak pemuda Al Kahfi yang keluar dari goa melakukan perlawanan (resist) pada sistem yang tiran. Jadi, sekali lagi, ini bukan sekuel buku tentang kepribadian Dallas mencapai mahqomnya. Salah kaprah.
Dari buku ini kita paham berada pada sistem yang mana. Dari buku ini, Dallas menunjuk ajar, bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan. New nomos. Inilah istilah yang digunakan. Bangunan jamaah baru, yang berisikan kaum pengusung fitrah tadi. New nomos tentu berbeda dengan new currenzy. Dalam new nomos sudah tentu akan ada new currenzy. Tapi menghadirkan new curenzy, belum tentu menghadirkan new nomos. Inilah makna utama pesan buku Dallas ini. Karena tak bisa sekedar berambisi menghadirkan new currenzy, bak pesannya soal ‘diassociate’ tadi. Saatnya membangun new nomos dengan futtuwa di dalamnya. Futtuwa is tassawuf. Ma’rifatullah is secret, kata Shaykh Abdalqadir as sufi. Tentu kaum yang berfuttuwa, tak bisa berjalan jika hendak mengelabui isi pesan makna buku ini, sekehendak hatinya. Dengan mendiskreditkan maknanya. Dengan mengecilkan isi kandungannya. Karena bukun ini membimbing kita pada sesuatu yang fitrah. Membangun kota keseluruhan fitrah. Itulah The Entire City.
Politik, ini sebuah aliran kekusaan yang berkembang masa Renaissance. Ian Dallas berkata, politik merupakan perpaduan antara realisme Aristotelian dan pragmatisme Machiavelli (The Entire City, 2015). Dari sanalah manhaj politik digodok. Era Renaissance, ‘politique’ menjadi jalan keluar dari kejumudan dogma. Karena sejak masa Romawi sampai Kekristenan, manusia masih meyakini bahwa kekuasaan merupakan Kehendak Tuhan. Tapi kemudian bergeser menjadi ‘kehendak Raja’ dan otoritas Gereja Roma. Reformasi Luthern dan Calvinis, sempat mereduksi kepercayaan itu. Tapi ujungnya, manusia dibawa kepada aliran politik sekuler.
Ini yang melahirkan ‘egalite, liberte, fraternite’ yang jadi slogan Revolusi Perancis. Robbiespierre kencang menyuarakan slogan itu. Seolah manusia harus memiliki free will (kehendak bebas) dalam menentukan pemimpin. Tak lagi terjerambab dalam urusan agama. Dielaktika ini berlangsung panjang. Epos pasca kegagalan crusaders, menjadikan krisis kepercayaan atas ‘kepemiminan atas nama agama.’ Ini yang jadi senjata para baron, kaum borjuis, untuk mengambil alih kekuasaan. Disitulah teori Maciavelli diminati.
Inti dari ‘Il Principe’ adalah penegasan bahwa seolah kekuasaan itu sepenuhnya ‘kehendak manusia.’ Bukan Kehendak Tuhan. Machiavelli, tentu merujuk Aristotelian, yang menganggap ‘being’ adalah perbuatan manusia. Bukan Perbuatan Tuhan. Ini masuk dalam domain aqidah. Ian Dallas mengatakan, “Pra renaissance, manusia meyakini manusia menjadi Tuhan. Pasca renaissance, manusia ‘menjadi’ Tuhan.” Karena manusia memiliki kehendak bebas. Doktrin filsafat mengajarkan, Tuhan bak pembuat jam. Kala jam selesai dibuat, maka jam berjalan sendirinya. Tuhan, bagi kaum filosof, hanya sebatas penyebab sekunder. Bukan penyebab primer.
Walhasil, urusan kekuasaan, Tuhan telah menyerahkannya pada manusia. Jadi, bukan sepenuhnya domain kaum agamawan. Dari sanalah, Machiavelli menelorkan bahwa penguasa adalah mereka yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Penguasa bukanlah given. Tapi yang mampu melahirkan sebuah tatanan wilayah berada pada kestabilan (Latin: statum). Kalimat ‘statum’ ini yang digunakan manusia modern. Inggris menterjemahkannya menjadi ‘state’. Belanda (staat). Perancis (L’etat). Jadi, penguasa seolah adalah sosok yang berhasil membuat wilayah menjadi ‘stabil’, tanpa kecamuk dan gejolak massa.
Abad pertengahan di Eropa, itulah gejolak aksi massa dan massa aksi sangat tinggi. Eropa springs terjadi. Perang antar aqidah, mewarnai belantara Eropa. Tahun 1517, pembantaian massal di istana Kerajaan Perancis, dalam peristiwa ‘Peringatan Hari Santobartolomeus’, menjadi titik awal krisis kepercayaan ‘Kekuasaan ditangan Raja.’ Dogma bahwa ‘Vox Rei Vox Dei’ (Suara Raja Suara Tuhan) seolah terbantahkan. Karena Raja dianggap wakil Tuhan, tapi kemudian terjadi pembantaian atas nama agama. “Apakah benar Tuhan mengkehendaki pembunuhan massal?” Tanya itu menjadi titik kritis yang tak terjawab. Ditambah masuknya filsafat, yang mewarnai renaissance, ditanggapi dengan ekstrim kalangan Gereja Roma. Itu makin menambah krisis logika bahwa ‘Raja adalah wakil Tuhan.’
Maka massa aksi berlangsung dalam dua golongan. Pengikut fatalisme dan ateisme saling berperang di Eropa. Bak pertarungan antara ‘jabariyya’ dan ‘qadariyya’. Jabariyya, menganggap segala sesuatu adalah ‘Kehendak Tuhan’, manusia tak memiliki daya dan kehendak apapun. Termasuk urusan kekuasaan, sepenuhnya adalah Kehendak Tuhan. Manusia harus patuh pada ‘Wakil Tuhan’, tanpa boleh dibantah, Tapi dogma ini memiliki banyak ‘kejanggalan historis’. Kegagalan ‘Crusaders’ menjadi titik kritis, tentang kepercayaan itu.
Sementara kaum ‘qadariyya’ yang dipeloposi filosof, membawa doktrin baru. Kekuasaan sepenuhnya ‘kehendak manusia.’ Inilah yang dipelopori Maciavelli, Thomas Hobbes, Jean Bodin, sampai Jean Jacques Rosseau. Mereka mengajarkan doktrin bahwa ‘Tuhan hanya penyebab sekunder.’ Bukan primer. Makanya manusia berhak menentukan tatacara kepemimpinan sendiri. Bukan lagi merujuk kaum agamawan.
Teori ini yang memiliki banyak pengikut. Disamping penumpang gelap mendompleng dalam ‘aksi massa’ gerakan ‘ateisme’ tadi. Merekalah kaum baron atau borjuis. Di Inggris, para baron yang mensponsori ‘King Willian of Orange’ melakukan Revolusi Inggris, untuk keluar dari otoritas Gereja Roma, 1669. Seabad kemudian, kaum borjuis Perancis, mendanai Robiespierre memimpin Revolusi Perancis, membantai kaum pengikut ‘agamawan dan bangsawan.’ Kota Paris jadi saksi sejarah, disitulah perang aqidah abad pertengahan, berlangsung home and away, antara pengikut ‘panteisme’ dan ‘ateisme’. Tahun 1572, kaum ateisme yang dibantai. Tahun 1789, kaum ateisme yang giliran membantai. Tapi kemenangan seolah berada ditangan pengusung ‘egalite, liberte, fraternite.’ Ini yang disangka Robbiespierre, dia telah merasakan kemenangan. Padahal dirinya hanya dijadikan boneka. Dua tahun memimpin revolusi, dia langsung disingkirkan. Para borjuis, mengkudetanya dengan mengangkat boneka baru: Napoleon Bonaparte.
Robbiespierre dan revolusioner Perancis merasa, keluar dari ‘kehendak Tuhan’ seolah itulah ‘liberte.’ Kebebasan. Meninggalkan hukum Tuhan, seolah itulah ‘egalite.’ Dan berkumpul bersama penganut ‘free will’ seolah itulah “fraternite” (persaudaraan). Padahal mereka kemudian berubah status. Perancis baru, dengan slogan Republik, bukanlah berubah menjadi ‘negara merdeka.’ Melainkan berubah status menjadi negara ‘koeli.’ Massa aksi memang berhasil ditenangkan. Aksi massa berhasil diredam. Tapi itu dilakukan dengan kediktatoran sebuah system. Karena manusia kemudian dikontrol dan dikendalikan oleh system. Sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi, tak ada yang namanya ‘freedom.’ Melainkan terkungkung oleh ‘sistem rule.’ Inilah gambaran utuh atas modernisme –buah dari renaissance-.
Revolusi Inggris, 1669, dan Revolusi Perancis, menjadi pertanda politik sekuler hanya menjadi jalan kekuasaan berada ditangan elit bankir. King William, berubah status menjadi boneka kaum bankir. Mereka menjadikan William sebagai Raja, tapi urusan keuangan, diambil sepenuhnya para baron. Maka berdirinya ‘Bang of England’ sebagai bank sentral. Napoleon idem ditto. Dia didapuk sebagai Kaisar, tapi kendali keuangan sepenuhnya ditangan elit bankir, itulah ditandai berdirinya ‘Bank de France.’ Bank sentral Perancis. Ian Dallas mengatakan, sesiapa mengendalikan harta, dialah penguasa. Maka, tak ada penguasa tanpa kontrol atas kekayaan. Politik sekuler, atas nama demokrasi atau Republik, telah memisahkan ‘penguasa dan pengendali harta.’ Maka tampaklah wujud modern state, dimana tak satupun ‘kepala negara’, mampu mengendalikan uang yang berlaku dinegaranya.
Perang Dunia II, menunjukkan kekuasaan bukanlah ditangan ‘head of state’. Bretton Wood, pasca PD II, menjadi indikasi bahwa para kepala negara tunduk di bawah otoritas bankir. Mereka dikumpulkan, diberi instruksi: “Mulai sekarang, kami menerbitkan uang kalian, tanpa ada lagi back up emas.” Itu instruksi bahwa kekayaan bukan lagi dibawah kendali Raja, Presiden ataupun yang disebut ‘penguasa.’ Jadi tampaklah seorang ‘head of state’ tak-lah berkuasa penuh. Revolusi Inggris, menabalkan hal demikian dengan disebut sebagai ‘monarkhi konstitusional.’ Artinya, kendali kekuasaan bukan sepenuhnya ditangan Raja. Melainkan dibawah kendali ‘constitutio.’ Siapa yang membuat konstitusi? Jean Jacques Rosseau yang punya teorinya. Constitutio, seolah lahir atas ‘kehendak manusia.’ Hukum bukanlah ‘Kehendak Tuhan.’ Maka, hukum harus dibuat oleh kawanan manusia. Bukan lagi merujuk pada Kitab Suci. Pasca Revolusi Perancis, Code Napoleon, jadi wajah terang bahwa manusia meninggalkan Kitab Suci. Dengan dalih bahwa manusia dibekali akal, untuk mengatur dunia. Inilah doktrin filsafat, yang melegitimasi manusia seolah berhak untuk membuat hukum sendiri. Descartes sampai Kant, menjadi biang kerok ajaran ini. Karena Descartes mengatakan, ‘Tuhan, manusia, alam semesta, dan lainnya, menjadi ajang penyelidikan manusia.’ Maka, manusia yang berhak dan menjadi ‘penentu.’ Doktrin ini yang meracuni dan melahirkan modernisme. Tuhan, dianggap sebagai penyebab sekunder. Bukan penyebab utama.
Teori ini diteruskan Hans Kelsen, sampai John Austin dengan positivism-nya. Seolah, ayat-ayat Kitab Suci, yang sah dan berlaku sebagai ‘hukum’, jika diletakkan dan tercantum dalam ‘constitutio’ dan aturan turunannya. Maka, sejak itulah modernitas resmi mengeliminasi Kitab Suci.
Begitu pula ‘politik’, yang diusung dari azas ‘free will’ tadi. Penguasa, secara resmi, bukanlah ‘Wakil Tuhan’ atas nama Raja. Robiespierre sampai Kemal Attaturk, secara resmi menyebutkan bahwa mereka bukanlah ‘Wakil Tuhan.’ Tapi, doktrin ini yang kemudian dihembuskan terbalik ke negeri-negeri muslim. Selepas modernisme menang di Eropa, kemudian merambah negeri-negeri muslim. Sampai kemudian menjatuhkan otoritas kebangsaan atas nama agama: sultaniyya. Dari situ doktrin baru diciptakan, bahwa seolah ‘Presiden adalah Ulil Amri.’ Padahal Attaturk sendiri secara tegas, dirinya mengkudeta dan membubarkan Daulah Ustamniyya, maka dia bukan sosok ‘Khalifah’ ataupun layak disebut ‘Ulil Amri.’ Tapi kini, kelumpuhan dan kejumudan berlangsung, sehingga membuat kelumpuhan umat. Karena faktanya, toh memang seorang ‘head of state’, tak mampu mengendalikan uang yang berlaku di negerinya sendiri. Karena itu adalah otoritas bankir. Stendhal berkata, ‘Tak ada penguasa tanpa mengendalikan harta.’ Simbolisasi harta adalah kekayaan. Sesiapa yang mengendalikan kekayaan, itulah sosok penguasa.
Politik sekuler hanya melahirkan dan menampakkan kekuasaan dibawah kendali kaum bankir. Doktrin diciptakan, untuk menjadikan kelumpuhan logika, karena seolah manusia berhak menentukan ‘kekuasaan sendiri.’ Padahal doktrin itu menjadikan manusia berada di bawah wujud ‘koeli-koeli.’ Ketika manusia lumpuh dan telah menjadi ‘koeli’, seolah tampaklah adanya ‘kestabilan’ (statum). Padahal itulah penindasan. Bukan ‘liberte.’ Politik sekuler, jelas tak lagi mampu membawa pada ‘kemerdekaan.’ Melainkan menjerumuskan pada per-koeli-an dunia. Karena penguasa sesungguhnya adalah kaum bankir. Mereka melegalisasi riba. Memaksa manusia modern tunduk pada sebuah sistem tunggal. Agama dianggap harus berada di bawah sebuah sistem yang diciptakan manusia, jika ingin berlaku. Inilah eliminasi terhadap Kebenaran Tuhan. Maka, kejumudan telah melanda modernisme.
Jalan keluar dari kejumudan ini, bukanlah kembali pada filsafat yang melahirkan politik sekuler. Melainkan kembali pada politik alamiah. Itulah absolut power. Islam merumuskannya dalam: sultaniyya. Pola kekuasaan merujuk Amal Ahlul Madinah. Inilah jalan keluar dari lubang biyawak. Artinya, bukan merujuk pada modernisme, dengan turunan-turunannya.
“Virtus et summa potestas non coeunt”
Futtuwa tidak cocok untuk kekuasaan yang absolut
{Lucan, sejarawan Romawi}
Kekuasaan jadi kosakata sepanjang epos jaman. Allah Subhanahuwataala berfirman: ”Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia…” (QS Ali Imran: 140).
Dan kamus kekuasaan ada dua: berbasis fitrah atau melawan fitrah. Fitrah itulah merujuk hukum alam. Melawan fitrah, itulah kekuasaan yang diperebutkan. Kekuasaan yang fitrah ialah yang tidak membawa konotasu politis apapun. Ini adalah karena Tuhan dan rakyat yang sangat menginginkannya (Ian Dallas, The Entire City).
Pola perjalanan kekuasaan inilah melahirkan bentuk sistem pemerintahan. Melongoklah jauh pada Polybios, pemikir Romawi (204-122 SM). Dia menelorkan “cyclus theori”. Dikenal cyclus Polybios. Lingkaran perjalanan model kekuasaan. Dari monarkhi, tirani, aristokrasi, oligarkhi, demokrasi, okhlokrasi dan kembali ke monarkhi. Itulah siklus. Dan jaman telah membuktikannya. Dari Polybios, melongok juga ke Ibnu Khaldun, abad 13. Tentang pola Sunnatullah peradaban. Karena sejarah telah membuktikan. Kaum bajik itu penanda untuk pembaca jaman.
Sifat kekuasaan pun terpola pada dua bagian. Civitas Dei atau Civitas Terrena. Ini teorinya Augustinus, Santo Nasrani dari Hippo Regius, pantai utara Afrika. Tahun 354-430 Masehi. Civitas Dei itulah yang merujuk Tuhan. Sementara Civitas Terrena itu sebutan yang berkiblat pada setan laknatullah.
Polybios mendedahnya dalam beragam model. Tapi sifatnya tak lepas antara Civita Dei atau Civitas Terrena. Dipergilirkan antara mengikut perintah Tuhan, atau tergelincir mengikut pola setan. Sampailah kita pada demokrasi. Pola yang kini dipuja bak religi. Karena demokrasi seolah setara dengan agama. Dipuja-puja, seolah tanpa-nya, hidup akan malapetaka. Padahal demokrasi hanya satu model pemerintahan. Bukan bentuk ‘negara’. Karena istilah ‘negara’ diambil dari kata ‘state’. Ini baru dikenal abad modern, pasca Revolusi Perancis, 1789. Itulah eksekusi dari ‘lo stato’ sebutan Machiavelli.
Tapi demokrasi, khalayak tak lagi peduli, apatah itu ‘Civitas Dei’ atau ‘Civitas Terrena’, model setan. Karena telah disembah tanpa pamrih. Ironinya, kaum agama justru menganggap itulah jalur untuk memenangkan agamanya. Mau Islam, Kristen atau kotak kosong sekalipun. Karena khalayak lupa tentang sejarah demokrasi, dan pola model pemerintahan yang dipergilirkan. Yang lebih ironi, khalayak masih yakin pola kini masih di tahapan demokrasi. Yang oleh Lincoln disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Padahal demokrasi dimulai dari modern era dimulai. Kala revolusi Perancis mereda. Disitulah semangat ‘vox populi vox Dei’ merajalela. Tapi itu sebuah kudeta. Pada pola kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan kaum oligarkhi di belantara Eropa. Yang telah panjang berdebat tentang sosok Tuhan. Karena eropa menimpor pola pemikiran filsafat, buah copy paste pemikiran Aquinas dari Ibnu Rusyd di Cordoba. Dari situlah filsafat berlangsung liar tak terkendali. Sampai menyelidiki tentang kebenaran Tuhan. Karena virtue di Eropa melemah. Francis Bacon berkata, Tuhan itu hanya ada dalam pikiran. Karena dia bilang: ‘Aku ada maka aku berpikir”. Akrobatiknya dilanjutkan Rene Descartes. Dia membaliknya teori induktif menjadi deduktif: “Aku berpikir maka aku Ada”. Immanuel Kant melengkapinya dengan empirisme. Ratio scripta. Inilah pondasi tentang ‘kebenaran’ versi baru. Kebenaran yang tak lagi berasal dari Tuhan. Alhasil, Gereja dan Raja tak dianggap lagi sah sebagai pemegang kekuasaan. Karena manusia dianggap lebih nomor satu mengatur kehidupan dunia. Bukan lagi dari Tuhan.
Kisah panjang Eropa meledak pada persoalan aqidah Nasrani.
Antara unitarian dan Trinitas. Antara Katolik dan Protestan. Abad 16, ribuan Huguenot, pengikut Protestan di Perancis, dibantai di depan Raja Louis. Lalu 3 abad berselang, 1789, giliran Huguenot membantai kaum Katolik dalam drama revolusi berdarah. Disitulah ‘vox Rei Vox Dei” dikudeta secara resmi. Berganti menjadi kedaulatan rakyat. Karena monarkhi telah berubah menjadi oligarkhi. Karena Raja sering bertitah ‘the king can do no wrong’. Bergeser pada oligarkhi, yang menuntut demokrasi. Perancis pun deklarasi, republik jadi panutan. Disitulah demokrasi jadi idaman. Konstitusi jadi pijakan. Buah pemikiran ‘le contract sociale’ alas Rosseou. Mereka mengidamkan Romawi, kala masa kebesaran. Demokrasi pun jadi religi. Menggantikan agama. Karena agama telah disingkirkan. Tuhan dianggap diktator. Tak layak lagi mengatur kehidupan manusia. Bak Voltaire berkata, segala kediktatoran haruslah ditolak, jika Tuhan ialah diktator maka Tuhan tak layak lagi. Ratio scripta membahana. Mereka mendambakan lagi masa Romawi.
Romawi memang kata penting. Inilah satu-satunya peradaban yang disebut dalam Al Quran: AR RUM. Karena Romawi menjejak hingga kini. Termasuk mimpi akan demokrasi. Dari sanalah kisah telah bermula. Bak pepatah orang Perancis berkata: ‘le histoire de repete’ (sejarah berulang). Romawi pun berulang. Karena kebesaran Europa ada pada Romawi. Kisah Romawi menjejak dari masa Romulus sampai Konstantinopel. Dan Islam yang menamatkan Romawi. Tatkala Sultan Muhammad II memimpin pembebasan Konstantinopel, 1453. Disitulah Romawi tamat, terwujudlah basyirah Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam.
Tapi Romawi punya kisah tentang fase pasca demokrasi. Simaklah masa Augustus menjadi Kaisar. Inilah periode Romawi menjadi kekaisaran pertama. Agustus (63-14 SM) merebut kekuasaan Kaisar Romawi. Pasca huruhara perang Triumvirat di Romawi. Agustus cucu dari Julius Caesar, yang dibunuh di depan senator oleh Brutus. Pembunuhan itulah membuat kejatuhan masa republik Romawi. Mark Anthony dan dirinya berebut kuasa. Tapi Legiun Romawi, sekumpulan pasukan elit, berpihak pada Augustus. Kemenangan pun tertoreh. Dia didaulat menjadi Kaisar pertama.
Fase Augustus itulah dimulai ‘imperium sine fine’ (Imperium tiada akhir). Inilah masa kelam Romawi. Karena Kaisar ternyata tak berkuasa. Kekuasaan diambil alih. Senator, yang selama ini mengontrol kekuasaan, telah diamputasi. Tak ada lagi pemegang kendali. Senator Romawi, tak bisa mengakses keuangan, apalagi mengontrol Kaisar. Republik pun mati suri. Karena era republik Romawi yang merujuk fitrah, dimulai kala Brutus I (bukan pembunuh Caesar), sampai menjelang tergulingnya Caesar. Disitulah Cicero membahanakan lagi. Dalam kitabnya: De Republica, Cicero menyuarakan betapa pentingnya Romawi kembali pada republik. Yang dalam bahasa Cicero, sistem yang merujuk ‘Divine Law”. Kodrat Tuhan. Bukan kodrat atas kehendak manusia.
Fase Augustus menunjukkan Romawi berada pada kehendak manusia. Itulah era ‘Civitas Terrena’. Bukan lagi Civitas Dei, seperti dimaksud Cicero. Karena Civita Dei berarti merujuk pada Divine Law. Era Augustus itulah Kaisar dibawah kendali, tapi tak resmi. Siapa pengendali? Itulah Legiun Romawi. Tytus Livy, sejarawan Romawi menceritakan tentang berkuasanya Legiun, mengendalikan Kaisar. Kekuasaan bukan berada pada Kaisar. Melainkan sosok dibalik layar Kaisar. Itulah masa kala rakyat, tribunal, diam seribu bahasa. Tribunal tak bersuara, karena passif menghadapi keadaan. Senator pun telah dibungkam. Dikebiri fungsinya. Karena senator tak lagi mengontrol. Itulah yang disebut era okhlokrasi atau mobocrazy. Bukan lagi demokrasi. Kekuasaan dikendalikan segelintir kaum perusak. Karena tak lagi patuh pada fitrah atau Divine Law.
Ian Dallas, dalam bukunya “The Entire City,” kitabnya tahun 2015, menceritakan hal fenomenal. Fase Augustan itulah yang kini terjadi. Dia membawa Republik Romawi pada penjelmaan Republik Amerika Serikat. Sebuah wujud modern state yang dianggap ideal –dari cita-cita atas nama demokrasi–.
Ian Dallas menulis:
“It was to be the identical claim of American Empire once the financial system had taken over power from the political class. The essential deception of the Augustan phase –that Empire was really republic because the form of the Senate had been maintained—was identical to that of the modern capitalist state, only the Legiun had been replaced by the Bank!’.
Dari situlah arti demokrasi telah berakhir. Karena ini telah masuk pola okhlokrasi. Mobocracy. Karena kekuasaan tak dikendalikan Presiden atau head of state. Kepala negara bukan pemegang tampuk kekuasaan. Melainkan dikendalikan oleh sosok dibalik itu: bankir. Mereka yang mengontrol dan mengendalikan negara. Maka, bukan lagi ada “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” seperti kata Lincoln. Tapi pemerintahan dari bankir, oleh bankir dan untuk bankir. Merekalah dibalik pengendali negara. karena seluruh bentuk negara kini, menjadi debitur bagi bankir. Utang nasional, atau utang negara, itulah pertanda. Karena tak ada satu pun state berdaulat mengatur uangnya sendiri. Melainkan di bawah kontrol bankir. Merekalah yang mengontrol negara. Dan itu jelas bukan lagi demokrasi. Bak Kaisar Agustus yang dikendalikan Legiun. Kini Legiun berubah menjadi Bankir.
Melongoklah pada pertemuan Presiden seantero dunia di bawah PBB, pasca Perang Dunia II. Di Bretton Woods, New Hampshire, dari 1 Juli hingga 22 Juli 1944. Itulah keputusan uang tak lagi berbasis emas dan Dollar Amerika Serikat sebagai patokan. Tapi, pertemuan itu pertanda dicabutnya secara resmi kewenangan Presiden sebuah negara, untuk mengendalikan uang. Semua kendali di bawah bankir. Dan, faktanya, 2018 lalu, utang Amerika mencapai 19.947 miliar dollar Amerika per Januari 2018! Ini fakta pengendali negara itulah bankir. Bukan Presiden. Jadi kekuasaan bukan berada ditangan Presiden. Tapi bankir, bak Legiun Romawi. Dan kini semua negara terjebak pada utang pada bankir. Dengan bunga berbunga yang bertambah. Imbasnya tentu pajak makin meninggi. Karena pajak itulah angsuran untuk membayar utang pada bankir. Atas nama negara, atas dalih demokrasi. Padahal ini sudah mobocracy. Okhlokrasi.
Inilah penyakit jaman. Ian Dallas menyebutnya, kapitalisme sebagai psikosis yang terstruktur secara sosial. Karena dibentuk dengan watak Civitas Terrena, sistem setan. Bukan fitrah.
Watak Civitas Terrena tentu kontra pada Civitas Dei. Kembali pada fitrah. Kembali pada peradaban merujuk Tuhan. Ian Dallas mendedahnya itu dimulai dengan new nomos. Peradaban baru. Masyarakat baru dengan pola fitrah. Karena penyakit psikosis jaman ini bukan riba pangkal sebabnya. Oleh karenanya tak sembuh hanya dengan antitesa muamalah semata. Melainkan menyeluruh dan utuh. The Entire City itulah wujud kota yang kaffah.
Islam telah memiliki pranata. Karena dalam Islam, semuanya telah clear menunjukkan sesuatu yang fitrah, yang berasal dari Allah Subhanahuwataala semata. Bukan dari kedaulatan rakyat, positivisme atau buah ratio scripta.
Dari Polybios kita bisa membaca, pasca okhlokrasi itulah akan kembali pada Monarkhi. Image monarkhi, bukanlah menuju pada monarkhi konstitusional, pasca diruntuhkannya nobility di kerajaan Inggris, abad 17. Melainkan monarkhi tatkala Brutus I menciptakan Romawi dengan tauhid. Itulah yang dikisahkan Cicero sebagai republik yang sesungguhnya. Itulah wujud monarkhi yang utuh. Dengan Divile law sebagai pondasi.
Karenanya, wajar Ian Dallas berkata: “…that in the present world there is simply nothing that can offer itself as a republic”.
(Bahwa di dunia kini tidak ada negara yang pantas disebut republik).
Lalu bagaimana republik yang ideal? Lihatlah Arnold Toynbee (1889-1975) sejarawan Inggris meninggal di Amerika Serikat. Dalam bukunya, “A study of History’: “The Ottoman institution came perhaps as near as anything in real life could to realizing the ideal of Plato’s republic”. (Kesultanan Utsmani adalah yang pernah ideal dalam menerapkan republik Plato). Nah, jadi republik itulah wujud sultaniyya.
Dallas pun mengajak untuk bersiap diri. Ini bukan lagi fase demokrasi. Melainkan okhlokrasi. Dari siklus Polybios terbaca, kemudian akan beralih menuju monarkhi. Bersiaplah menyambut masa ini. era yang disebut interim. Hamlet berkata, “Interim is mine”. Raihlah interim itu agar menjadi milikmu. Kembali pada peradaban fitrah, Civitas Dei dengan Divine Law.
Karena kedaulatan rakyat itulah bentuk menyekutukan Tuhan. Syirik. Kembali pada kedaulatan Tuhan. Fitrah.
“Politik menghancurkan taqwa.” (Ian Dallas, The Entire City, 2015).
Politik, ini hanya sebuah aliran. Sebuah cara dalam melihat tentang kekuasaan. Mahzab ini berkembang sejak era renaissance di Eropa. Seiring masuknya filsafat ke Eropa. Kaum barat mengambilnya dari mu’tazilah. Ini masa kala filsafat “di-Islam-kan.” Renaissance itu, ketika filsafat “di-Kristen-kan.” Makanya azas free will kemudian berkembang meruak masa rennaisance. Azas itu digunakan melawan dogma Gereja Roma. Ajaran yang kala itu berkembang dominan. Dari situlah ‘politik’ dikenali. Istilah aslinya disebut “political science.’ Sains politik. Tapi era modern, jamak hanya mengenalnya sebagai ‘politik.’
Dasar-dasar ilmu politik, kaum modern mengenalnya dari tokoh renaissance. Mulai Machiavelli hingga Jean Jacques Rosseau. Kontrak sosial menjadi pondasi utama. Dari Machiavelli, seolah melompat langsung pada Plato dan Aristoteles. Karena kaum modern seolah melewati ‘sanad’ lahirnya ‘politik’ itu bukan berasal dari mu’tazilah. Karena sebelumnya, Al Farabi, sampai Ibnu Rusyd, telah mengajarkan lebih dulu perihal pola kekuasaan merujuk mahzab politik. Dari sanalah Thomas Aquinas, Machiavelli, Montesquei dan lainnya, mengutipnya. Tentu ini hanya perulangan sejarah. Bukan “penemuan” baru seperti klaim kaum barat Eropa.
Tapi mahzab politik tak serta merta berjaya. Machiavelli harus bersembunyi untuk menuliskan Il Principe. Karena doktrin didalamnya, bertentangan dengan dogma masa itu. Il Principe, mengajar bahwa Pangeran (Raja), bukanlah sebuah given (pemberian berlandas keturunan). Melainkan manusia yang bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. Penguasa, katanya, haruslah tegas bak binatang buas dan licik seperti kancil. Ini demi terciptanya kestabilan (statum) dalam kerajaan. Dari kalimat “statum” inilah muncul kata “lo stato” (Italia), Jerman/Belanda (staat), Inggris (state), France (le etate). Maka, sejak itu ajaran perihal “state” berkembang besar. Pandangan Machiavelly seolah sebuah jalan melawan dogma. Karena landasan utama Il Principe, mengajarkan bahwa manusia memiliki ‘kehendak bebas’ (free will) tadi. Ini ajaran yang berasal dari filsafat. Karena filsafat membawa manusia seolah memiliki ‘kehendak bebas’.
Dari ‘kehendak bebas’ itulah manusia berhak menentukan siapa yang berhak menjadi raja. Bukan berlandas pada atensi dan pemberian dari Gereja Roma. Karena jaman itu, Gereja Roma yang memegang kendali atas penentu dari siapa yang berhak menjadi Raja, di sebuah wilayah. Maka raja-raja yang tergabung dalam liga, berkumpul dalam Imperium Romanum Socrum. Kekaisaran Romawi Suci. Mereka menterjemahkan Raja sebagai wakil Tuhan. Adagium yang berkembang pun: Vox Rei Vox Dei (Suara Raja Suara Tuhan).
Dari tekanan itulah aliran politik mencuat. Pasca Machiavelli, muncul lagi Montesquei. Filosof Perancis. Dia menelorkan teori yang diikuti hingga kini. Trias Politica. Seolah kekuasaan tak bisa ditangan seorang Raja. Tentu dasarnya untuk menentang mekanisme dogma. Montesquei menteorikan kekuasaan harus separation of power. Dibagi tiga. Eksekutif, legislative, yudikatif. Intinya dia memaksa bahwa manusia berhak menentukan Bagaimana pola kekuasaan dijalankan.
Dari sana disambut lagi oleh Jean Bodin. Yang merumuskan konsep ‘republik’ sebagai wadah perwujudan ‘kekuasaan manusia.’ Bodin menyalahi Cicero tentunya. Karena Cicero, dalam kitabnya Republik, meyakini kekuasaan itu wujud Kehendak Tuhan. Bukan ‘kehendak manusia.’ Bodin menafsir paksa, kekuasaan bukanlah ‘kehendak Tuhan.’ Dia mengkisahkan tentang ‘soverignty’ (kedaulatan), yang sepenuhnya ‘kehendak manusia.’ Manusia berhak berdaulat penuh dalam menentukan penguasa dan kekuasaan wilayah. Tak boleh ada campur tangan dari otoritas agama. Dia mengkritik pengaruh Raja yang kala itu dibawah kendali Gereja Roma. Itu dianggapnya kekuasaan Pangeran tanpa ‘sovereignty’ (kedaulatan).
Thomas Hobbes tak berbeda. Leviathan, kitabnya, meneruskan ajaran Aristoteles. Manusia dianggap sebagai ‘zoon logicon.’ Hobbes menganggap manusia bak binatang buas. Zoon politicon. Makanya perlu kontrak sosial. Aturan bersama yang disepakati. Aturan itu yang melahirkan ‘state.’ Kestabilan. Dasar ‘zoon logicon’, tentu karena menilai manusia itu memiliki ‘kehendak bebas.’ Bukan makhluk yang diamati. Melainkan makhluk yang mengamati.
Hobbes tentu parsial dalam memahami anatomi manusia. Imam Ghazalii telah memberikan ajaran paripurna. Manusia, kata Imam Ghazali, memiliki tiga sifat. Sifat malaikat, sifat hewan, dan sifat setan. Hanya salah satu yang mendominasi. Dan itu Nampak dari perilakunya. Jika perilakunya adalah banyak bersyukur, ibadah, berdzikir, maka inilah manusia yang mengenyam sifat Malaikat. Inilah manusia yang sukses. Tapi jika perilakunya bak hewan, suka berkelahi, suka memangsa, terlalu banyak makan, suka mencengkeram sesama, itulah yang mengandung sifat hewan. Shaykh Abdalqadir al Jailani membagi lagi sifat hewan itu terbagi dua. Hewan buas dan hewan ternak. Nah, Hobbes hanya mendefenisi bahwa manusia itu bak “zoon logicon.” Binatang buas. Makanya perlu diatur dengan aturan bersama. Yang dibuat manusia juga. Itulah lahir istilah “contract social.” Kemudian ada sifat setan. Inilah manusia yang berperilaku penuh dengan kelakuan iri, dengki, hasad, ghibah, suka mabuk-mabukan, penuh angkara murka, hanya ber-orientasi pemenuhan syahwati. Ini sifat setan.
Leviathan-nya Hobbes hanya memberi ajaran bahwa manusia itu bak binatang buas. Makanya, solusinya tak paripurna. Tapi ini yang dijadikan pondasi utama dalam aliran “politik.”
Puncaknya muncul Jean Jacques Rosseau. Filosof Perancis lagi. Dia mengklimakskan perihal ‘le contract sociale.” Manusia harus membuat hukum bersama. Karena manusia, katanya, dibekali dengan akal untuk membuat aturan. Akal itu dianggap sebagai pemberian Tuhan. Ini khas ajaran filsafat. Rosseau menterjemahkan itu dalam konsep kekuasaan. Manusia tak bisa mematuhi Raja, tanpa adanya sebuah kontrak. Kontrak itu datang dari rakyat, kepada Raja. Teori Rosseau ini yang diamalkan Robbiespierre. Penggerak utama revolusi Perancis, 1789. Dialah yang mempraktekkan teori Rosseau dan aliran politik, dalam Perancis modern. Setelah mengkudeta otoritas Raja dan Gereja. Maka tak ada lagi dogma, yang berkuasa. Pengikut politik, itulah yang mengusung azas “free will.” Kehendak manusia. Sementara mereka bertentangan dengan pengikut Gereja Roma, yang meneruskan dogma ‘Kehendak Tuhan.’
Tapi kita harus melongok dulu pada kejadian “massacre de Paris.” Tahun 1548. Ini kala kaum filosof masih belum dominan. Kala teori politik masih samar-samar. Massacre de Paris ini kejadian mencekam. Pengikut Hugueanot dibantai dalam peristiwa “Hari Santo Bartolomeus.” Ini Sahabat-nya Isa Allaihisalam, yang dibantai Romawi kala berdakwah dulu. Kaum Nasrani kerap memperingati hari ‘pembantaian’ itu saban tahun. Tapi peringatan itu, juga berujung pembantaian. Yang disasar adalah pengikut Huguenot. Mereka yang mengikuti ajaran John Calvin maupun Marhin Luthern. Kedua tokoh Nasrani itu tak setuju dengan dogma Gereja Roma selama ini. Karena dianggap banyak terjadi hal iirasionalitas. Mereka menuntut reformasi pada Gereja Roma. Ingat, masa itu kekuasaan raja-raja Eropa berada di bawah pengaruh Gereja. Jadi reformasi Gereja, juga berdampak pada otoritas kekuasaan.
Paris jadi kota saksi perang antar keduanya. Kejadian “Massacre de Paris”, pengikut Huguenot yang diburu. Tapi Revolusi Perancis, 1789, giliran kaum pengikut Gereja Roma yang diburu dan dibunuh. Dan ini mempengaruhi ‘aliran politik’ menjadi berkembang.
Tapi “massacre de Paris” (1548) itulah yang mengubah peta Eropa. Aliran politik makin diminati. Karena dianggap Raja telah “abuse of power”. Menyalahgunakan dogma “Kehendak Tuhan”. Tapi disisi lain ada sekelompok juga yang menentang Gereja dan Raja. Itulah kaum Monarchomach. Mereka juga tak setuju dengan pola kekuasaan ala Gereja Roma itu. Monarchomach ini banyak dari kalangan alim Nasrani juga. Francois Hotman (1524-1590) menentang habis kejadian “massacre de paris” yang dianggap penyimpangan kekuasaan. Hotman menganggap hal itu sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan. Tapi Hotman tak menghendaki pola “political science.” Melainkan berteguh pada penguasa berhak diganti, jika menyimpang. Kemudian muncul yang popoler, Dupplesis Mornay. Karena sebuah artikel panjang bertebaran seantero Eropa, pasca pembantaian berdarah itu. Artikel itu berjudul “Vindiciae Contra Tyranoss.” Perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Penulisnya memakai nama samara: Brutus. Ini diambil dari tokoh Romawi, yang menikam Julius Caesar di Senat Romawi. Tapi menurut Ian Dallas, sang Brutus itulah Dupplesis Mornay. Dia memperjuangkan perlawana pada tirani kekuasaan, dengan pola tetap berpegang pada “Kehendak Tuhan.” Bukan keluar dari teori “kehendak Tuhan” dan menyeberang menjadi “free will.” Mornay menjelaskan Bagaimana pola kekuasaan harus dijalankan dengan adil.
Mornay menggambarkan pola kekuasaan berganti pada era Julius Caesar. Raja tirani berhak dibunuh dalam senat, jika memang menyimpang. Tanpa perlu mengganti system. Ini juga diperkuat oleh Theodore Beza (1511-1602). Dia ini murid John Calvin. Dia menentang teori “political science.” Aliran politik. Karena hal itu dianggapnya menyimpang dari “Kedaulatan Tuhan.” Beza meyakini kekuasaan tetap merupakan kehendak Tuhan sepenuhnya. Manusia hanya menjalankan perintah-Nya. Jika terjadi penyimpangan, maka pola pergantian Raja lalim wajib dilakukan. Dan itu dilakukan di lingkaran alim ulama.
Dari sana kemudian muncul juga John Locke. Tokoh Inggris ini tak setuju dengan politik. Locke menjelaskan, “Wahyu tetap diperlukan karena ada manusia yang menyalahgunakan akalnya.” Teori Locke bertentangan dengan Bodin. Locke menilai kedaulatan itu adalah buah munculnya ‘duel contract.’ Kekuasaan itu adanya dua kontrak. Kontrak Raja pada Tuhan dan kontrak raja pada rakyat. Sementara Bodin, Hobbes, sampai Rosseau hanya menganggap ‘contract sosial” itu hanya antara Raja dan rakyat. Tapi mengeliminasi ‘peranan’ Tuhan. Disinilah Locke tidak bersetuju.
Abad 20, muncul tokoh pengusung lagi teori “Monarchomach” dari Inggris. Dialah Harold Laski. Dia bukan seorang komunis. Tapi merupakan anak ideologis dari Mornay. Laski menjelaskan perlunya kini dilakukan re-evaluasi terhadap teori “state.” Karena sanad lahirnya “state” berasal dari “lo stato/state/staat/le etate” tadi.
Muncul dari teori politik Machiavelli sampai Rosseau. Laski menilai, “kehendak bebas/kehendak rakyat” tak serta merta menjamin kestabilan (statum).
Laski mencuatkan kembali “hukum alam” dalam pola kekuasaan. Bukan dengan pola hukum ala manusia (ration law).
Dari Laski inilah kemudian Ian Dallas, mencuatkan kembali perihal aliran Monarchomach sebagai solusi. Karena selama hampir 4 abad, aliran politik mendominasi dunia, terbukti mengalami kegagalan. Revolusi Perancis, menjadi titik awal “politik” dipergunakan. Virusnya kemudian menyebar seantero dunia. Tapi “politik menghancurkan taqwa,” kata Ian Dallas. Karena pondasi ‘politik’ adalah ‘kehendak bebas,’ yang menganggap manusia berhak menentukan kekuasaan dengan “ration scipta.’ Kekuasaan model ini telah disalahgunakan dan menyimpang. Karena realitasnya tak ada negara yang memiliki sovereignty seperti teori Bodin. Melainkan negara berada di bawah kontrol ‘supra state’. Inilah yang muncul seiring dengan munculnya ‘modern state.’ Supra state inilah kaum bankir, yang mengontrol ‘alat tukar’ setiap negara. Mereka memiliki kekuasaan, dengan memanfaatkan teori ‘kehendak bebas.’ Makanya abad 20 keatas, menjadi bukti kegagalan politik. Ketika manusia meninggalkan pola kekuasaan berlandas ‘Kehendak Tuhan’ dan menggantinya dengan ‘kehendak manusia,’ disitulah muncul kelemahan. Ordo bankir menggantikan otoritas Gereja, yang dikudeta masa Revolusi Perancis. Otoritas bankir inilah yang kemudian menentukan siapa yang berhak menjadi ‘presiden’ dan ‘raja’ di sebuah state. Pola ini bisa dilihat dari Bretton Wood, tahun 1946. Kala penguasa negara-negara, harus tunduk dan patuh pada bankir. Tak ada ‘kedaulatan.’ Makanya jika Lincoln berkata, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu telah berubah. Pemerintahan dari bankir, oleh bankir dan untuk bankir. Demokrasi telah berubah menjadi mitos. Tak pernah menjadi realitas.Maka keluar dari jebakan ‘kehendak bebas’ inilah yang sejatinya telah diwanti Imam Ghazali, Shaykh Abdalqadir al Jailani sampai Ibnu Khaldun. Mereka merekomendasi Supaya “kehendak bebas” itu tak sepenuhnya dipergunakan. Tapi tetap dengan ‘kehendak Tuhan.” Pola Kehendak Tuhan inilah jalan kekuasaan bisa stabil (statum) diemban. Pola ini yang terus dilakukan umat Islam sejak dulu. Sebagaimana Wali Songo dalam membangun Kesultanan Demak. Dan kala Orhan Ghazi membangun Utsmaniyya. Mereka tak menggunakan “politik.” Melainkan kembali pada kekuasaan berlandaskan fitrah. Duel contract. Karena kontrak sosial, terbukti dikooptasi. Karena politik menghancurkan taqwa.
 POLITIK VS MONARCHOMACH
POLITIK VS MONARCHOMACH  Ajang Pemilukada (Tertutup) 2024 Nir Mandat (Judi Coblos) bukanlah Jalan Perubahan Daerah-Negara
Ajang Pemilukada (Tertutup) 2024 Nir Mandat (Judi Coblos) bukanlah Jalan Perubahan Daerah-Negara 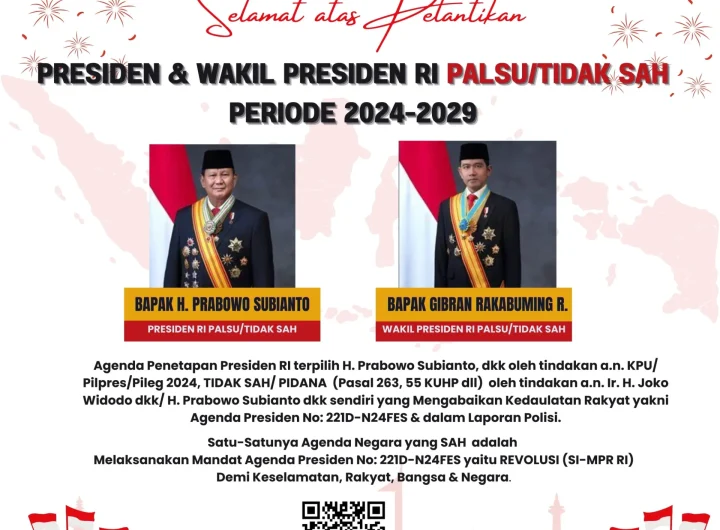 PRESIDEN RI Bapak H. PRABOWO SUBIANTO, dkk TIDAK SAH/ILEGAL, Dokumen Pelantikannya PALSU.
PRESIDEN RI Bapak H. PRABOWO SUBIANTO, dkk TIDAK SAH/ILEGAL, Dokumen Pelantikannya PALSU.